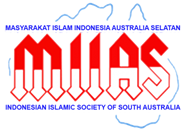ika saja semasa hidupnya Rasulullah Saw. menjelaskan ilmu pengetahuan alam dan astronomi, maka aktivitas penginderaan dan penalaran manusia niscaya akan berakhir sampai di situ, dan manusia akan dimanjakan dengan itu semua. Akan tetapi, Rasulullah justru menyarankan manusia agar menggunakan indera dan kecerdasannya guna mengkaji segala hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan, memperluas pengetahuan, dan memperkaya jiwa. Dengan demikian, pintu untuk menyingkap ilmu pengetahuan semacam itu adalah kecerdasan dan eksperimen, bukan hadis dan ilmu-ilmu agama.
– Muḥammad ‘Abduh (1849-1905)-
KECEPATAN CAHAYA DAN USIA DUNIA MENURUT ALQURAN
Sekitar satu dasawarsa lalu, seorang astronom Mesir muda yang cerdas menceritakan sebuah makalah yang baru ia baca. Ia menilai, makalah tersebut adalah tulisan paling mengesankan yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Saya kira makalah yang ia maksud adalah makalah sains, karena itulah saya penasaran untuk mengetahui isinya meskipun bidang keahlian perhitungan dalam makalah tersebut utamanya didasarkan pada sebuah ayat Alquran berikut: Dialah yang mengatur urusan kosmik dari langit hingga bumi kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya (yakni melalui alam semesta) pada suatu hari yang kadar (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Alquran, Surah as-Sajdah/32: 5). Sebagai perbandingan dan untuk menyajikan beberapa implikasi penting, di sini saya menyisipkan terjemahan versi Yusuf Ali terhadap ayat tersebut sebagaimana berikut: “Ia yang mengatur (semua) urusan dari langit ke bumi: pada akhimya (segala urusan) akan naik kepada-Nya di suatu Hari yang kadar (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu“. Perlu dicatat bahwa hari yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari kiamat, bukan hari-hari biasa.
Penulis makalah tersebut kemudian menggabungkan ayat ini dengan beberapa kuantitas-kuantitas astronomi dan geometri secara artifisial hingga mendapatkan nilai c (laju cahaya) yang sangat dekat dengan hasil eksperimen (yaitu 299.792,46 km/s).
Kesalahan konseptual dan metodologis utama yang dilakukan oleh Hassab-Elnaby adalah sebagai berikut:
- Ayat tersebut hanya membahas waktu, tidak menyebutkan jarak. Karena itu, hasil perhitungan laju cahaya berdasarkan ayat itu tidaklah valid. (Lihat Lampiran B tentang bagaimana penulis memperkenalkan konsep jarak secara artifisial).
- Penulis memanipulasi kuantitas-kuantitas fisika demi mendapatkan hasil yang tepat, kadang-kadang “mengatur” persamaan-persamaan dengan pencantuman artifisial cosinus dari sebuah sudut atau nilai rata-rata dari suatu jumlah tertentu (misalnya, jarak bulan-bumi yang bervariasi sepanjang tahun dan bahkan sepanjang waktu).
- Alquran menyebutkan seribu tahun menurut perhitunganmu, yang berarti bulan-bulan sinodis, bukan bulan sideris sebagaimana yang digunakan Hassab-Elnaby.
- Hassab-Elnaby menjejali pembaca dengan berbagai istilah teknis dan konsep fisika, termasuk intepretasi keliru atas teori relativitas khusus. Jika metode ini benar-benar kuat, ia semestinya dapat memberi penjelasan yang sesederhana dan sejernih mungkin.
- Jika seseorang bisa menghitung jarak yang ditempuh oleh ‘semua urusan’ untuk mencapai Tuhan dalam satu ‘hari’ (1.000 tahun), ini menunjukkan bahwa (1) Allah berada dalam radius jarak tertentu dari kita manusia dan (2) diperlukan beberapa waktu untuk mencapai-Nya.
- Beberapa penulis menunjukkan bahwa gagasan satu hari yang setara dengan seribu tahun juga muncul dalam Perjanjian Baru: Bagi Tuhan, satu hari sama seperti seribu tahun (2 Petrus, 3: 8). Yang lebih penting, kata ribu dalam budaya Arab kuno berarti ‘sangat banyak’ atau jauh lebih besar dari yang biasa digunakan manusia dalam hidup keseharian.
Lalu mengapa kita harus susah-susah membahas makalah yang mengandung kesalahan serius ini? Tidak adakah klaim-klaim menggelikan yang lain? Sebenarnya banyak, tetapi makalah tersebut mencerminkan dua hal. Pertama, bagaimana seorang Muslim mendekati Alquran. Kedua, bagaimana gaya pendekatan tersebut berdampak terhadap kebudayaan Islam. Selain tersebar begitu luas, gagasan ini juga telah direproduksi dalam bentuk yang lebih buruk, yakni dalam sebuah buku karya Zaghloul An-Najjar berisi 600 halaman dengan 200 gambar full colour yang sudah terbit dalam empat edisi. Dalam buku tersebut, Profesor An-Najjar meluangkan satu halaman khusus untuk membahas derivasi laju cahaya yang dimulai dengan persamaan berikut:
Laju benda-benda kosmik = 1.000 tahun/hari
menurut perhitungan manusia.
Namun, setiap mahasiswa dapat segera menilai bahwa secara fundamental, persamaan ini salah. Laju (speed) tidak pernah bisa menjadi rasio dari dua periode waktu. Karena itu, ketika hasil persamaannya adalah 334,056.8 km/s, An-Najjar mencoba mendapatkan hasil yang tepat (300.000 km/jam) dengan menggunakan ‘saran’ Hassab-Elnaby, yakni mengalikan ‘faktor bulan’ dan ‘faktor tahun’ yang masing-masing ia sebut sebagai ‘rasio bulan sideris/bulan sinodis’ yakni 27.32/29.53 = 0,9252′ dan ‘rasio 309 tahun lunar/300 tahun matahari’ yang ia anggap setara dengan 0,97087. Satu hal yang hilang di sini adalah cosinus sudut yang diperkenalkan secara artifisial oleh Hassab-Elnaby. Kita justru mendapat beberapa angka baru yang secara “abrakadabra” dikalikan berkali-kali-hanya untuk menghasilkan nilai yang diinginkan (dan/atau sudah diketahui sebelumnya).
Derivasi versi An-Najjar yang cukup berbeda tersebut sangatlah penting, sebab versi tersebut menjustifikasi bahwa angka-angka dapat digunakan dan digabung satu sama lain untuk mendapatkan hasil final yang diinginkan, bukan karena angka-angka tersebut masuk akal dalam kerangka konseptual yang koheren.
Sayangnya, perhitungan Elnaby dan An-Najjar bukanlah akhir cerita. Pendekatan yang mereka gunakan tampaknya telah berkembang menjadi ‘aliran’ tersendiri dengan para pengikut yang menerapkan metodologi yang sama untuk masalah-masalah lain yang sejenis.
Pada Juli 2007, saya menerima sebuah makalah berjudul ”A New Method for Estimating the Ages of the Earth and of the Universe” yang ditulis Profesor Kamel Ben Salem. Coba perhatikan kesamaan judul makalah tersebut dengan makalah Hassab-Elnaby. Dalam karyanya, Ben Salem menggunakan metodologi yang saya kritik di atas secara persis. Ia memulai paparannya dengan ayat Alquran: Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada-Nya dalam sehari yang kadarnya sama dengan lima puluh ribu tahun (Alquran, Surah al-Ma‘ārij, 70: 4) yang kemudian menjadi pusat tesisnya dan diperkuat dengan ayat berikut ini: Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu sama seperti seribu tahun menurut perhitunganmu (Alquran Surah al-Ḥajj, 22: 47; al-Sajdah, 32: 5). Selain itu, dalam makalah tersebut, ia juga kerap menggunakan ungkapan-ungkapan seperti “relativitas waktu dalam Alquran”. Untuk memulai derivasinya, ia mengungkapkan bahwa “salah satu sahabat Nabi menyadari bahwa ayat tentang 50.000 tahun menunjukkan kurun waktu yang memisahkan awal penciptaan dan hari akhir (Hari Perhitungan)” dengan operasi perkalian berikut:
1 hari = 50.000 tahun = 50.000 x 365.256.363.051
‘hari dunia’ = 18.262.818.152 ‘hari dunia’
dan setiap ‘hari dunia’ bernilai 1.000 tahun,
sehingga kurun waktu berdasarkan perhitungan ini adalah 18.262.818.152 tahun menurut perhitungan manusia.
Ben Salem kemudian juga mengutip beberapa ayat lain (seperti, Alquran, Surah Qāf, 50: 38 dan Fuṣṣilāt, 41: 9-10) sehingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa total jatah waktu yang diberikan kepada alam semesta (dari penciptaan sampai hari kiamat) adalah delapan ‘hari’ (atau periode P) dengan rincian 6 periode P berdasarkan masa kosmologi lampau, sedangkan dua yang terakhir merupakan usia bumi. Dari langkah sederhana inilah, diperoleh sebuah hasil:
umur bumi, TE =2 P = (18.262.818.152/8) x 2 = 4.565.704.538 tahun atau 4.5657 milyar tahun; usia alam semesta, TU = 6 P = 6 x (18.262.818.152/8) = 13.697.113.614 tahun, yaitu 13,7 miliar tahun;
Sehingga waktu yang tersisa antara saat ini dan Hari Kiamat adalah 4.5657 miliar tahun meskipun dalam hal ini Ben Salem tidak menunjukkan secara jelas karena umat Muslim umumnya menganggap hari Kiamat sebagai pengetahuan eksklusif ilahi. Ben Salem hanya menyebutnya dengan istilah “waktu yang tersisa untuk tata surya.”
Lalu, apa yang bisa kita tarik dari ‘derivasi’ semacam itu? Tidak banyak, selain catatan bahwa Ben Salem harusnya mengetahui bahwa perkiraan terbaru atas usia semesta (13,7 miliar tahun) yang diperoleh dari data WMAP hampir sama dengan tiga kali usia bumi (4.540.000.000 tahun) yang sudah diketahui luas berdasarkan US Geological Survey. (Perhatikan bahwa rasio 3: 1 ini hanya bisa dianggap mendekati kebenaran di zaman kita saat ini, dan belum tentu dapat bertahan selama, katakanlah, 100 juta tahun mendatang.) Dengan catatan ini, setiap Muslim jangan menganggap bahwa rasio 3:1 diturunkan dari beberapa ayat Alquran yang membicarakan penciptaan langit dan bumi dalam empat hari, dua hari, dan lain sebagainya. Begitu juga, akan sangat mudah disimpulkan bahwa 1/4 (atau 2/8) dari 50.000 x 365 menghasilkan angka 4,5 juta, sehingga jika angka ini dikalikan dengan 1.000, akan diperoleh hasil 4,5 miliar tahun sebagai umur bumi. Sisa digit angka dalam derivasi -yang sebenarya tidak bermakna apa-apa itu- hanya digunakan untuk membesar-besarkan kesan saja.
Meskipun saat ini semakin sedikit orang yang terkesan dengan perhitungan numerik di atas, saya ingin menunjukkan bahwa ketika Ben Salem tengah membangun ‘metode barunya’ yang sepenuhnya didasarkan pada beberapa ayat Alquran, Zaghloul An-Najjar dan Marwan At-Taftanazi juga menggunakan ayat-ayat yang sama dalam buku mereka masing-masing dan membuat kesimpulan bahwa bumi pasti diciptakan sebelum penciptaan bagian-bagian kosmos yang lain. Berikut saya kutipkan ungkapan An-Najjar (profesor geologi) mengenai hal ini:
Alquran menyatakan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di bumi sebelum mengubah langit berasap pertama menjadi tujuh langit (Alquran, Surah AI-Baqarah/2: 29). Kemudian Surah Fuṣṣilāt/41: 9-12 menyatakan bahwa semua elemen yang diperlukan kehidupan di bumi, bahkan bumi purba itu sendiri, sudah diciptakan sebelum pemisahan langit berasap pertama menjadi tujuh langit. Jadi, bisakah para ahli astronomi, astrofisika, dan geologi Muslim merevisi teori-teori dan perhitungan ilmiah dewasa ini berdasarkan ayat-ayat Alquran untuk menguatkan bahwa fakta-fakta tersebut adalah i’jaz? Ketika para ahli sepakat mengenai unsur-unsur berat hanya bisa diciptakan di alam semesta khususnya di dalam bintang-bintang, revisi yang demikian akan sangat berguna untuk memperkuat kepercayaan Muslim dan mengundang non-Muslim (untuk juga percaya) bahwa orang-orang tersebut sebenarnya terlalu tergoda oleh sains dan data-datanya yang membawa mereka tersesat dan hilang arah.
Hampir sama dengan pernyataan di atas, Marwan At-Taftanazi (ahli I’jaz yang lain) mengemukakan hal berikut:
Ayat-ayat ini (Alquran, Surah Fuṣṣilāt/41: 9-11) menguatkan fakta kosmik yang sudah mapan dan pasti, bahwa setelah awal ‘pemisahan’, bumi diciptakan pertama kali, kemudian dibentuklah langit dari ‘asap’ primordial. Sementara itu, para penafsir yang tidak ingin mencocokkan ayat ini dengan teori-teori ilmiah -yang menganggap penciptaan langit terjadi sebelum bumi, sebenarnya melakukan kesalahan serius,
Malek Bennabi (l905-1973) -seorang pemikir Aljazair yang sangat disegani, dengan buku pertama dan terpentingnya, The Quranic Phenomenon, yang ditulis khusus untuk mengeksplorasi berbagai karakteristik Alquran dan pengalaman Nabi mengenai fenomena-fenomena alam-juga tergoda dengan konsep I’jaz dan meluangkan satu bab khusus untuk membahas ‘kandungan ajaib ilmiah’ di balik beberapa ayat tertentu. Satu hal yang paling menakjubkan dari pernyataannya adalah penjelasan mengenai ‘Ayat Cahaya’ yang sudah terkenal (Alquran, surah an-Nūr/24: 35, seperti yang dikutip sebelumnya) dengan menyamakan ceruk sebagai proyektor, lampu sebagai kawat pijar, dan kaca sebagai bola lampu. Sayangnya, kesalahannya bukan hanya dalam pernyataan ini, sebab ia juga melontarkan beberapa interpretasi keliru lainnya yang tak kalah mengejutkan.
FENOMENA KEBUDAYAAN YANG BERKEMBANG
Teori I’jaz ‘ilm (‘mukjizat ilmiah’) Alquran ini telah berkembang cepat dan menjadi bagian besar yang tak terpisahkan dalam lanskap budaya Dunia Islam (utamanya bangsa Arab) selama beberapa dekade terakhir, sehingga menjamurlah berbagai kajian mengenai ‘konten ilmiah dalam Alquran’. Pencarian singkat di dunia maya terhadap referensi seputar topik ini akan menampilkan berbagai artikel buku, semisal Subatomic World in the Quran , Science and Sunnah: the Genetic Code, The Grand Unification Theory (GUT): Its Prediction in Alquran, dan Islam and the Second Law of Thermodynamics. Karya-karta tersebut ditulis untuk menunjukkan, misalnya, bahwa Alquran lah yang meramalkan penemuan telepon, fax, e-mail, radio, telegram, televisi, laser, pulsar, dan lubang hitam.
Dalam otobiografi intelektualnya, Desperately Seeking Paradise, Sardar membela tesis sains Islaminya dari serangan salah seorang temannya yang sangat skeptis terhadap seluruh konsep yang ditawarkan Sardar dan melontarkan ungkapan: “Ide Anda mengenai sains Islami telah dibajak oleh kaum fundamentalis dan mistik. Para fundamentalis mencari mukjizat ilmiah dalam Alquran, sehingga segala hal, mulai dari relativitas, mekanika kuantum, teori big bang, hingga kajian embriologi dan beberapa kajian geologi modern dianggap telah “ditemukan” dalam Alquran”.(Terkait dengan aliran ‘mistik’, lawan bicara Sardar tersebut merujuk aliran Nasr.)
Harus juga saya tekankan di sini bahwa sebagian besar pendukung metode ini adalah orang-orang terdidik, dan terlepas dari proposisi-proposisi mereka yang dengan mudah bisa dimentahkan atau disalahkan, mereka benar-benar tulus ketika mencoba mengukuhkan (kebenaran) pernyataan autentik Alquran.
Salah satu gagasan paling mencolok dalam literatur Islam adalah klaim bahwa Alquran berisi “segala jenis pengetahuan” -yang kadang-kadang ditambah dengan pernyataan “yang ada dari zaman kuno hingga zaman modern”. Gagasan ini biasanya diperkuat dengan ayat Alquran berikut: Tiadalah Kami alpakan (abaikan) sesuatu apa pun di dalam al-Kitab (Alquran, Surah Al-An‘ām/6: 38). Namun, kaum modernis (reformis) menafsirkan ayat ini hanya sebagai petunjuk bahwa Alquran memuat prinsip-prinsip umum dari segala hal yang penting diketahui manusia. Belakangan, kecenderungan lain muncul pada abad ke-20 dengan klaim bahwa prinsip “segala jenis pengetahuan ada di dalam Alquran” harus diperluas dan mencakup sains modern, sehingga segala hal yang telah dan akan diciptakan oleh manusia juga bisa ditemukan dalam teks-teks Alquran, apabila Alquran benar-benar dieksplorasi dengan cermat.
Ada dua versi dari kecenderungan terakhir ini: (a) aliran ‘tafsir ilmiah’ (tafsīr ‘ilmī) yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah modern harus digunakan bersama perangkat-perangkat keilmuan lain untuk lebih memahami beberapa ayat Alquran yang tidak bisa ditafsirkan dengan tepat pada zaman dahulu, dan (b) aliran ‘mukjizat ilmiah Alquran’ (I’jaz ‘ilmi) yang mengklaim bahwa beberapa ayat Alquran, jika dibaca dan ditafsirkan ‘secara ilmiah’, cukup eksplisit mengungkapkan sebagian kebenaran ilmiah yang ditemukan belakangan ini; karena itulah Alquran dianggap sebagai keajaiban ilmiah yang berasal dari Tuhan.
Belakangan ini, aliran tersebut tidah hanya populer, tetapi juga mendapat dukungan resmi. Bahkan, di Makkah didirikan Komisi untuk Mukjizat Ilmiah Alquran dan Sunnah di bawah Liga Muslim Dunia yang hingga kini menerbitkan belasan buku tentang topik seperti “mukjizat-mukjizat Alquran dalam geologi” dan menyelenggarakan sembilan konferensi internasional di berbagai negara. Bukti popularitas dan dukungan resmi terbaru yang diterima ‘aliran’ ini adalah penghargaan Dubai International Holy Quran Award yang diberikan oleh Islamic Personality of 2006 kepada Zaghloul An-Najjar, tokoh terpopular dalam aliran tersebut.
Sebelum membahas teori I’jaz, saya ingin terlebih dahulu membahas pendekatan lain yang lebih moderat dan sering disebut dengan ‘penafsiran ilmiah’. Penafsiran ini mendukung pemanfaatan pengetahuan ilmiah dalam interpretasi Alquran.
TAFSĪR ‘ILMĪ (PENAFSIRAN IIMIAH)
Tidak seperti At-Taftanazi, An-Najjar (sebagaimana penulis-penulis lain) membedakan dengan jelas antara pendekatan I’jaz (berikut tujuan-tujuannya) dan tafsīr ‘ilmi. Sikap An-Najjar tersebut tampak dalam pernyataannya berikut ini:
Ketika menyebut ‘i‘jaz ilmiah’, yang ada di pikiran kami adalah tersedianya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Alquran mendahului sains modern dalam fakta-fakta tentang kosmos atau adanya penjelasan Alquran tentang fenomena alam berabad-abad sebelum adanya penemuan sains. Sementara itu, tafsīr ‘ilmī adalah upaya manusia untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai beberapa ayat Alquran. Jika upaya ini berhasil, upaya penafsiran tersebut akan mendapat dua pahala (satu karena sudah mencoba, dan satu lagi karena berhasil -menurut tradisi Islam), sedangkan jika gagal, ia hanya menerima satu pahala.
Aliran penafsiran Alquran ini berhubungan erat dengan gerakan reformasi yang muncul sekitar pertengahan abad ke-19 dengan pemimpin-pemimpin seperti Sir Seyyed Ahmad Khan, Jamaluddin AI-Afghani, dan Muḥammad ‘Abduh. Beberapa pemimpin tersebut sama-sama mencurahkan perhatian serius baik dengan cara ‘membuktikan’ potensi modern Islam vis-a–vis Barat maupun dengan melahirkan gerakan kebangkitan dari kalangan umat Muslim demi menggalakkan sikap-sikap modern di bidang penalaran dan kemajuan. (Beberapa penulis mengklaim bahwa penafsir Alquran pada masa klasik abad ke-12, Fakhr Al-Din AI-Razi, harus dianggap sebagai pelopor aliran ini, karena sering menggunakan pengetahuan ilmiah pada zamannya dalam karya tafsirnya). Khan dan para reformis bersikeras bahwa Alquran dan alam semesta harus dianggap sebagai perjanjian antara Tuhan dan manusia, sehingga tidak ada kontradiksi karena keduanya mencerminkan keselarasan.
Dalam tafsir Alqurannya -yang belum tuntas namun cukup ambisius-’Abduh sering menggunakan sains dalam menafsirkan ulang beberapa konsep dan peristiwa yang disebutkan dalam ayat-ayat Alquran. ‘Abduh begitu bersemangat menggunakan sains dalam bagian-bagian akhir penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena alam. Sayangnya, tak ada satu pun dari para reformis ini yang dapat dianggap sebagai pelopor kecenderungan penafsiran ilmiah, sebab penafsiran ilmiah bukanlah tujuan utama mereka. Yang mereka lakukan sebenarnya adalah menyelaraskan Alquran dengan sains dalam rangka menunjukkan modernitas yang melekat dalam Islam.
Menurut Islamolog Rotraud Wieland, pendekatan penafsiran ilmiah pertama kali digunakan oleh Muḥammad Al-Iskandarani, seorang dokter yang sekitar tahun 1880 menulis dua buku dan diduga “mengungkap rahasia Alquran mengenai benda-benda langit dan bumi, hewan, tanaman, dan zat-zat logam”. Langkahnya tersebut diikuti oleh beberapa pemikir lain dengan agenda yang lebih berani, khususnya Thanthawi Jauhari yang pada 1923 menghasilkan sebuah ensiklopedi penuh mengenai nilai-nilai ilmiah Alquran, yang dilengkapi gambar dan tabel. Dengan ensiklopedi tersebut, Thanthawi berupaya menunjukkan bahwa Alquran berisi banyak ‘permata’ pengetahuan (seperti judul bukunya, Jawāhīr).
Sebelumnya, para pemikir terkenal telah menggunakan pendekatan ini dalam menafsirkan Alquran. Pada zaman klasik, ada seorang jenius berwawasan luas di bidang kesusasteraan dan polymath) Al-Jāhizh (781-869), teolog Andalusia dan ahli hukum Ibn Hazm (994 -1064), dan Al-Ghazālī (1058-1111), sedangkan pada zaman modern ada Al-Kawākībī (1849-1905).
Para pendukung terbaru pendekatan tafsir ilmiah di antaranya adalah ahli bedah Prancis yang terkenal Maurice Bucaille (meskipun ia kadang-kadang lebih cenderung pada ‘mukjizat ilmiah Alquran’), Wahid Ad-Din Khan, Muḥammad Jamal-Eddine Al-Fendi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Muḥammad Mutawalli As-Sya’rawi, Mustansir Mir, Jalees Rehman, Abd-Al-‘Alim Abdul-Rahman Khudr, dan bahkan Muḥammad TaIbi (dalam hal-hal tertentu). Dalam artikel terbaru mengenai masalah ini, Rehman mengutip beberapa contoh berikut ini sebagai “upaya menjelaskan ayat-ayat Alquran dengan sains modern”, seperti penjelasan mengenai “banjir pada masa Nabi Nuh sebagai peristiwa mencairnya lapisan es”, “penyakit karena konsumsi daging babi dan alkohol”, dan lain-lain. Barangkali, karena juga menyadari kelemahan program tersebut, ia menambahkan, “Banyak penulis [dengan upaya yang sama] yang memiliki niat baik dan sering percaya bahwa pengungkapan korelasi Alquran dan sains modernlah yang menghasilkan Islamisasi sains”. Ia juga mengakui, “Salah satu bahaya dari upaya mengaitkan sains modern dengan Alquran adalah karena upaya ini telah membuat semacam keterkaitan antara nilai-nilai dan kebenaran Alquran yang abadi dengan ide-ide sains modern yang bersifat sementara.”
Saya akan memberi beberapa contoh tentang bagaimana tafsir ini bekerja. Pertama-tama biasanya dilakukan penyaringan atau pelacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam, misalnya Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir (berdampingan); Yang satu tawar dan segar, dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan dinding dan batas yang menghalangi antura keduanya (Alquran, Surah Al-Furqān/25: 53) atau ayat Dan matahari berjalan di tempat peredarannya (Alquran, Surah Yā Sīn/36: 38). Kemudian, proses ini dilanjutkan dengan menghimpun semua pengetahuan ilmiah untuk mencoba menarik penjelasan yang paling masuk akal (atau setidak-tidaknya konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang mapan ketika itu). Karena itulah, Wahid Ad-Din Khan menggunakan konsep “tegangan permukaan” di air yang komposisinya berbeda untuk menjelaskan ayat pertama yang dikutip di sini. Sementara itu, Muḥammad Abduh menggunakan teori aktivitas gunung berapi bawah laut untuk menafsirkan ayat kedua dan teori astronomi modern untuk menggambarkan gerakan matahari dalam ayat Alquran, Surah Yā Sīn/36: 38.
Seorang cendekiawan Muslim klasik yang sangat berpengaruh karena menggunakan pendekatan saintifik beberapa abad yang lalu adalah Ar-Rāzī dengan karyanya Mafātih Al-Ghayb atau Kitāb At-Tafsīr Al-Kabīr. Dalam karya-karya tersebut, ia menggunakan banyak teori sains, sehingga dalam beberapa hal ia tak jarang membingungkan pembaca dengan diskusi astronomi atau karena terlalu menyimpang jauh dari tema yang diangkat dalam sebuah ayat. Ia sendiri menyadari sikapnya yang berlebihan itu, kemudian berusaha membenarkan pendekatannya dengan mematahkan beberapa kritik yang dilontarkan kepadanya seperti tampak dalam tulisannya berikut:
Barangkali, orang-orang bodoh dan apatis akan berkata: Sikap Anda yang terlalu mengait-ngaitkan penafsiran atas Kitab Allah ini dengan astronomi telah menyalahi norma. Menanggapi pikiran dangkal ini, kami menjawab: Jika Anda pernah merenungkan Kitab Allah secara mendalam dan benar, Anda akan menyadari kesalahan dalam keberatan Anda itu. Pembelaan atas apa yang kami lakukan berasal dari dua sisi: pertama, Allah sendiri yang mengisi Kitab-Nya dengan contoh-contoh dari langit dan bumi untuk menekankan konsep pengetahuan, kekuatan, dan kebijaksanaan dari-Nya yang la ulang-ulang dalam berbagai ayat dan sural. Yang kedua, pernyataan-Nya berikut: Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar (urusannya) dibandingkan penciptaan manusia. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui (Alquran, Surah Gāfir/40: 57), sehingga mengabaikan pentingnya pemahaman terhadap fenomena langit.
Banyak cendekiawan menyatakan keberatannya terhadap pendekatan ini. Berikut ini adalah para penentang aliran tersebut, di antaranya yang paling terkemuka: Pada zaman klasik, ada As-Syatibi (1388), ahli hukum Islam Andalusia, dan pada abad ke-20 ada Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, dan Sayyid Qutb. Alasan di balik keberatan tokoh-tokoh tersebut dirangkum oleh Wielandt dalam beberapa poin berikut: (a) aliran tersebut sering memunculkan makna kosakata Alquran yang tak dapat dipertahankan; (b) meremehkan sebab-sebab turunnya wahyu (asbab an-nuzul) dan konteks tekstual dari ayat-ayat yang sedang ditafsirkan, dan (c) menghilangkan konteks sosial dan budaya masyarakat di balik ayat-ayat yang ditafsirkan. Sementara itu, penulis kontemporer Sami Ahmad Al-Musili menambahkan dua poin yang lebih kritis berikut ini: (1) Dalam tafsir ilmiah, Alquran yang sempurna dibuat tunduk pada pengetahuan (sains) manusia yang tidak sempurna dan (2) pendekatan ini bersifat elitis dan eksklusif sehingga tidak dapat diakses oleh semua umat Muslim. Menurut saya, poin-poin yang disebutkan di atas bukanlah masalah yang serius, setidak-tidaknya karena dua alasan. Pertama, tiga poin yang pertama sebenarnya mengabaikan gagasan bahwa Alquran tidak boleh terikat pada budaya Arab abad ke-7 dan harus relevan untuk semua orang, dan karena itulah para pendukung aliran penafsiran ilmiah mencurahkan segala upaya intelektualnya untuk mewujudkan gagasan ini. Kedua, semua keberatan di atas mengabaikan gagasan utama yang saya anjurkan dalam buku ini, yakni bahwa Alquran mengandung banyak lapisan makna dan karenanya bisa dilihat oleh pengetahuan sebelumnya (yang dimiliki seseorang sebelum membaca Alquran), sehingga Alquran bisa mencerahkan jika direfleksikan karena memiliki kecenderungan ilmiah atau sastrawi serta mengandung gagasan rasional atau spiritual.
Dalam sebuah artikel yang lebih mutakhir, Mustansir Mir mempertimbangkan kelangsungan proyek penafsiran ilmiah tersebut. Dalam upayanya mempertahankan pendekatan ini, ia menunjukkan bahwa penafsiran ilmiah harus dianggap pertama-tama sebagai sebuah pendekatan terhadap Alquran sebagaimana pendekatan-pendekatan lain yang telah muncul sebelumnya (linguistik dan teologis). Kemudian, pendekatan ‘ilmiah’ ini harus dianggap muncul sebagai respons atas kebutuhan nyata dan konkret. Dewasa ini, dominasi sains dan pandangan dunia ilmiah tampaknya akan mendorong bahkan memaksa digalakkannya tafsīr ‘ilmi(tafsir ilmiah). Ia memberi dukungan atas pendekatan ini dengan alasan sebagai berikut:
Secara linguistik, sangat mungkin sebuah kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu lapisan makna, sehingga sebuah lapisan makna tertentu bisa diterima suatu khalayak pada masa tertentu pula, sedangkan lapisan makna lain yang tidak meniadakan lapisan pertama, bisa diterima khalayak lain pada masa berikutnya.
Demi menguatkan idenya, ia memberi contoh berikut:
Kata yasbahūn (berenang atau mengapung) dalam ayat “Dan Dialah yang menciptakan malam dan siang serta matahari dan bulan yang masing-masing keduanya ‘mengapung’di dalam garis orbitnya (Alquran, Surah aI-Anbiyā’/21: 33)” bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat Arab abad ke-7 yang mengamati fenomena alam dengan mata telanjang, tetapi juga (dimengerti dan diterima oleh) kita hari ini yang telah memiliki penemuan-penemuan ilmiah, yaitu mekanika benda langit.
Mir sebenarnya sangat kritis terhadap beberapa ‘penafsiran ilmiah’ amatir yang dangkal informasi dan telah muncul di mana-mana, terutama di dunia maya. Ia menyimpulkan bahwa “tidak ada penafsiran ilmiah terhadap Alquran yang kredibel hingga hari ini” dan “seperti halnya di dunia tasawuf, tafsīr ‘ilmī mungkin harus menunggu muncul seorang Ghazālī-nya sendiri”. Saya setuju dengan ungkapan tersebut.
I’JAZ ‘ILMĪ: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS SINGKAT
Banyak penulis menganggap kecenderungan tren ini bersumber dari Nabi sendiri melalui beberapa hadis beliau, para sahabat beliau, atau melalui pengakuan sahabat-sahabat beliau. Nabi diriwayatkan pernah bersabda bahwa “keajaiban Alquran tidak terbatas” sehingga beliau memerintahkan umat Muslim untuk “menggali makna Alquran dan memecahkan misteri-misterinya”. Demikian pula, salah satu sahabat utama Nabi, Abdullah bin Mas‘ud, diriwayatkan pernah mengatakan: “Siapa pun yang ingin menguasai pengetahuan orang-orang dahulu dan orang-orang yang akan datang, ia harus mempelajari Alquran secara mendalam”. Saya harus menambahkan di sini bahwa banyak temuan lain yang juga membenarkan kemukjizatan konten ilmiah Alquran tersebut dalam hadis (dan wacana klasik lainnya) dan semakin mengukuhkan Alquran sebagai ‘mukjizat’ Nabi.
Beberapa penulis lain mempertimbangkan temuan berharga dari para teolog dan ahli hukum klasik termasyhur, Al-Ghazālī (w. 1111) dan As-Suyūtī (w. 1505), yang sangat terkesan dengan ayat-ayat Dan Kami turunkan Al Kitab (Alquran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu (Alquran, Surah an-Naḥl/16: 89) dan Tiadalah Kami alpakan sesuatu apa pun di dalam Al Kitab (Alquran, Surah Al-An‘ām/6: 38). Dengan retorika yang agak berlebihan, mereka pun menyerukan bahwa Alquran berisi semua pengetahuan yang bisa dipikirkan (thinkable). Al-Ghazālī mempertahankan gagasannya mengenai ‘penafsiran dengan opini pribadi’ (tafsīr bi ar-ra‘y) dan menunjukkan bahwa pernyataan Nabi dan Abdullah ibn Mas’ud di atas sangat jelas menyiratkan keharusan seseorang untuk melampaui setiap pembacaan yang dangkal terhadap Alquran. Dalam buku terkenalnya, Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn, ia menulis demikian: ‘Alquran memiliki simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk yang hanya dapat dipahami oleh para ahli; maka dapatkah pembacaan yang dangkal bisa mengungkap makna di balik ayat-ayat tersebut?” Lebih lanjut beliau mengatakan dalam buku beliau selanjutnya, Jawāhīr Alquran: “Pernahkah Anda mendengar bahwa Alquran adalah samudera yang menjadi muara dari semua pengetahuan, dari yang terdahulu hingga yang terkemudian, seperti halnya sungai-sungai dari berbagai pantai bermuara di lautan?” Dengan analogi yang sama, ia menyamakan eksplorasi terhadap Alquran layaknya penemuan kerang, kemudian menyamakan tingkatan orang yang mendekati Alquran, dari hanya mengagumi, menggosok, hingga membuka kerang untuk menemukan mutiara di dalamnya.
Namun, seperti yang ditekankan Ahmad Dallal, dua ayat di atas (Alquran, Surah An-Naḥl/16: 89 dan Al-An‘ām/6: 38) -jika dibaca lebih saksama- sebenarnya mengarah kepada pengetahuan tentang akhirat. Ia bahkan bersikeras mengatakan bahwa “terlepas dari klaim keduanya, baik Al-Ghazālī maupun As-Suyūtī tidak benar-benar mengorelasikan teks Alquran dengan sains dalam sebuah prosedur penafsiran yang sistematis”. Dallal kemudian menunjukkan bahwa kecenderungan yang demikian tidak pernah muncul pada masa keemasan Islam, bahkan ketika sains berada di puncak pekembangannya Banyak orang mengklaim bahwa ledakan I’jaztermutakhir dimulai oleh Maurice Bucaille, ahli bedah Prancis yang pada 1976 menerbitkan buku berjudul La Bible, Ie Coran et la Sain: Les ecritures saintes examinees ala lumiere des connaissances modernes (“Bibel, Alquran, dan Sains: Kitab-Kitab Suci dalam Tinjauan Sains Modern”) yang di dalamnya menyatakan bahwa Alquran bukan hanya tidak mengandung pernyataan yang bertentangan dengan temuan ilmiah terbaru, melainkan juga berisi berbagai referensi mengenai fakta yang tidak bisa terungkap sejak 14 abad yang lalu. Dalam versi bahasa Prancis, buku tersebut telah diterbitkan dalam 14 edisi dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa di seluruh dunia. Buku tersebut merupakan sensasi instan di Dunia Muslim, dan Dr. Bucaille kemudian menjadi ikon budaya. Peneliti mana pun tidak akan ragu mengatakan bahwa reputasi tersebut sebenarnya dipengaruhi statusnya sebagai seorang Prancis dan seorang dokter serta misteri tak terungkap apakah dirinya memeluk Islam atau tidak.
Dalam buku yang ia tulis bersama Muḥammad TaIbi (Reflexions sur Ie Coran), diceritakan bagaimana ia mempresentasikan temuannya di depan Academie Nationale de Medecine dalam kuliah yang ia sampaikan tak lama setelah penerbitan bukunya:
Dalam buku saya, saya menampilkan berbagai tema yang sama sekali tidak memuat pertentangan sekecil apa pun antara teks-teks Alquran dan sains modern. Skenario penciptaan dunia dalam Alquran-berbeda dengan Bibel -secara keseluruhan sesuai dengan ide-ide modern tentang susunan alam semesta, penelitian tentang benda-benda langit, gerakan dan evolusinya, serta dengan gagasan yang akhir-akhir ini baru muncul, termasuk prediksi penjelajahan ruang angkasa, refleksi terhadap siklus air di alam, dan bentuk bumi yang diterima beberapa abad kemudian. Semua pengamatan ini -yang tentu saja dapat mengejutkan siapa pun yang melihatnya secara objektif- berpotensi menggeser fokus saya ke level pertanyaan yang dimensinya lebih luas. Namun, pertanyaan yang harus tetap diajukan adalah: apakah kita di sini hanya akan diam saja melihat adanya berbagai fakta yang sangat menentang kecenderungan alamiah kita dan hanya menjelaskan segala hal dengan pertimbangan-pertimbangan materialistik? Memang, keberadaan pernyataan-pernyataan ilmiah dalam Alquran menjadi tantangan tersendiri bagi kemanusiaan.
Seperti yang dapat kita lihat dengan jelas, Bucaille bergeser dari sebuah pendekatan tafsīr ‘‘ilmī yang menjanjikan sumbangsih besar menuju I’jaz ‘ilmī. Dalam buku yang ditulis bersama TaIbi, ia menyediakan banyak ruang untuk memperkuat pendapatnya tentang wacana sains dalam Alquran.
Kasus yang serupa dengan Bucaille dialami Profesor Keith Moore yang pada 1986 menerbitkan sebuah artikel berjudul ”A Scientist’s Interpretation of References to Embryology in the Quran” dalam The Journal of Islamic Medical Association. Moore adalah seorang profesor anatomi dan pernah menjabat sebagai pembantu dekan sains-sains dasar di Fakultas Kedokteran University of Toronto. Moore akhirnya juga menjadi selebriti di Dunia Muslim (meskipun reputasinya lebih rendah dibandingkan Bucaille) berkat pernyataan-pernyataannya itu. Setelah mengkaji ayat-ayat Alquran yang (secara singkat) menggambarkan tahap-tahap perkembangan embrio, ia berkesimpulan:
Penafsiran ayat-ayatAlquran mengacu kepada perkembangan manusia yang tidak mungkin terjadi pada abad ke-7 Masehi, atau bahkan seratus tahun yang lalu. Saat ini, kita dapat menafsirkannya karena sains modern mengenai embriologi telah memberikan pemahaman baru. Dan yang pasti, ada banyak ayat lain dalam Alquran tentang perkembangan manusia yang akan dipahami di masa mendatang seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita.
Satu hal yang perlu dicatat dalam analisis Moore adalah bahwa ia hanya mengacu kepada satu terjemahan saja, yakni terjemahan versi Abdelmajid Az-Zandani (pendukung kuat I’jaz)! Karena itulah, dapat dipahami mengapa Moore membuat penafsiran yang mengesankan dan menarik kesimpulan yang seantusias itu.
Meski demikian, marilah kita membaca ayat-ayat berikut dengan pikiran terbuka dan perspektif netral: Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (Alquran, Surah al-Mu’minūn/23: 14); Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu dalam berbagai tahap yang datang silih berganti dalam tiga fase kegelapan (Alquran, Surah Az-Zumar/39: 6); dan beberapa ayat lain (misalnya, Alquran, Surah al-Ḥajj/22: 5) yang mirip dengan dua ayat sebelumnya.
Kesimpulan rasional yang mungkin muncul di benak kita adalah bahwa gambaran-gambaran tersebut bersifat umum dan bernilai benar menurut kapasitas keilmuan masing-masing orang di beberapa generasi yang berbeda. Satu hal yang sulit dibuktikan dari klaim-klaim Az-Zandani dan pendukung I’jaz adalah keberadaan ‘fakta-fakta’ yang ditemukan baru-baru ini. Mengatakan bahwa banyak pengetahuan tentang alam semesta (tubuh manusia, gerak langit, dan lain-lain) yang sudah diketahui sejak dulu namun sering tidak dipahami, bukan berarti merendahkan Alquran; justru inilah gerbang masuk bagi sains modern. Saya yakin bahwa ini hanyalah salah satu di antara sekian banyak kasus tersebut.
Saya kira, dua contoh pendekatan I’jaz versi Bucaille dan Moore adalah gerbang perkenalan yang baik untuk mendalami metodologi I’jaz meskipun keduanya memiliki kekurangan masing-masing. Dua versi tersebut juga menjelaskan bahwa para pendukung pendekatan ini secara bertahap bergeser dari menggunakan pengetahuan ilmiah untuk bisa memahami secara lebih baik ayat-ayat Alquran tentang fenomena alam -metode yang digagas dan dipraktikkan oleh ‘Abduh dan para pemikir lain- menuju penafsiran ayat-ayat Alquran yang diklaim membahas eksplorasi ruang angkasa, radio, relativitas, lubang hitam, dan kecepatan cahaya.
METODOLOGI I’JAZ: DALAM TEORI
Zaghloul An-Najjar memperkenalkan agenda utamanya untuk membuktikan bahwa kemukjizatan Alquran mendahului berbagai penemuan ilmiah modern dengan melontarkan beberapa pernyataan berikut. Pertama, ia menegaskan bahwa susunan Alquran sering disampaikan dengan gaya bahasa yang bisa dipahami secara bermacam-macam oleh generasi yang berbeda-beda, tetapi tidak bertentangan satu sama lain. Karena itulah, dengan meluasnya bidang pengetahuan, sains, dan lainnya dewasa ini, pemahaman kita terhadap berbagai ayat Alquran bisa jadi sangat berbeda dengan pemahaman generasi-generasi sebelum kita. Sampai di titik ini, saya setuju dengan pendapatnya.
Akan tetapi, ia terlalu eepat membuat lompatan besar dengan mengklaim bahwa Alquran mengandung begitu banyak informasi ilmiah. Ia mengaku mendapatkan ‘pembenaran’ atas pernyataannya ini berdasarkan ayat-ayat berikut: Setiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) memiliki waktu (kejadian tertentu) yang kelak akan kamu ketahui (Alquran, Surah al-An‘ām/6: 67); Kami akan memperlihatkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami kepada mereka di segenap ufuk dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Alquran adalah Kebenaran. Tidakkah .cukup bagimu bahwa Tuhanmu menyaksikan segala sesuatu? (Alquran, Surah Fuṣṣilāt /41: 53); dan Dan Alquran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Alquran setelah beberapa waktu lagi (Alquran, Surah Ṣād/38: 87-88).
Setelah itu, ia kemudian menentukan pedoman-pedoman I’jaz yang dipetakan menjadi sepuluh prinsip berikut:
- Memahami teks Alquran dengan baik dan sesuai dengan aturan pemaknaan bahasa Arab.
- Mempertimbangkan ‘ilmu-ilmu Alquran’ terdahulu (semisal, asbāb an-nuzūl, ayat yang di-nasīkh, dan hadis-hadis yang menjelaskan ayat-ayat tertentu, dan lain-lain).
- Menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan sebuah topik umum sebelum melangkah pada penafsiran baru.
- Menghindari penafsiran yang berlebihan dan tidak ‘memelintir’ ayat-ayat agar bisa sesuai dengan temuan ilmiah.
- Menjauhi isu-isu yang ‘tak terlihat’ (gaib atau pengetahuan eksklusif ilahiah).
- Fokus pada sebuah tema secara khusus ketika menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan topik tertentu
- Mempertahankan ketepatan dan kejujuran intelektual ketika berhadapan dengan pernyataan ilahi.
- Menggunakan fakta-fakta ilmiah yang sudah mapan, bukan teori-teori yang belum pasti atau sekadar dugaan, kecuali dalam ayat-ayat Alquran dan pernyataan Nabi tentang penciptaan dan kemusnahan alam semesta serta tentang kehidupan dan manusia. Beberapa topik ini memang tidak memungkinkan observasi dan determinasi, sehingga pengetahuan manusia di bidang ini hanya berada pada tingkat dugaan. Umat Muslim sendiri bisa -dengan menggunakan ayat-ayat dari Kitab Suci atau Sunnah (tradisi Nabi)- membantu menguatkan teori yang masih bersifat dugaan itu untuk naik ke tingkat kebenaran yang mapan
- Membedakan tafsīr ‘ilmī dan I’jaz ‘ilmī, baik dalam Alquran maupun Sunnah. Dalam tafsīr ‘ilmī ada beberapa kasus yang belum bisa dipastikan hasilnya oleh ilmu-ilmu manusia, sehingga sah-sah saja menggunakan teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu, misalnya tentang alam semesta. Jika teori tersebut belakangan diketahui kesalahannya, kesalahan dilimpahkan kepada penafsir, bukan kepada Alquran. Namun, dalam I’jaz ‘ilmī, seorang penafsir harus menggunakan fakta-fakta ilmiah yang telah benar-benar mapan saja, sehingga ia tidak bisa mengklaim mukjizat Alquran atau kenabian mendahului pernyataanpernyataan yang kelak bisa jadi akan dianggap salah.
- Menghormati upaya-upaya ulama sebelumnya dalam segala hal yang terkait.
Jika diamati, sebagian besar pedoman di atas tampaknya agak trivial, tidak fundamental, dan terlalu terpaku pada aturan-aturan metodologis akademik yang umumnya diajarkan di depan mahasiswa untuk dipatuhi. Namun, seperti yang kita akan lihat di sepanjang tulisan ini, masalah utamanya adalah bahwa beberapa praktisi bidang I’jaz justu jarang sekali -bahkan hampir tidak pernah- berpegang pada metodologi di atas.
Penting dicatat di sini bahwa pedoman nomor 8 dan 9 di atas mempakan kaidah yang baru dan kontroversial. Dalam beberapa hal, pedoman nomor 9 dapat diterima dengan dalih ‘usaha intelektual manusia’ dan ‘dorongan melakukan ijtihād’ (upaya intelektual untuk menghasilkan pandangan baru yang mungkin lebih berguna dibandingkan pandangan lama). Saya pun yakin bahwa segelintir ulama ortodoks akan membolehkan ‘para ahli’ untuk memproyeksikan pemahaman ilmiahnya dalam penafsiran teks-teks suci. Di sisi lain, pedoman nomor 8 adalah proposisi yang menakjubkan: Profesor An-Najjar bersedia membiarkan -dan bahkan mendorong- para peneliti menggunakan ayat-ayat Alquran untuk ‘mengunggulkan’ sebuah teori (katakanlah teori alam semesta tertutup/closed universe) daripada teori lain (misalnya teori alam semesta terbuka/open universe), sebagaimana (kesalahan) yang ia lakukan!
Saat ini, salah satu isu yang juga krusial dalam teori ini adalah keutamaan Alquran di atas pengetahuan ilmiah versus kemandirian sains dalam berbagai metode dan hasil temuannya. Dua pandangan tersebut sama-sama dapat ditemukan di kalangan para pendukung teori ini dengan asumsi berikut:
- Seseorang tidak perlu terburu-buru mencari referensi Alquran untuk menguatkan penemuan ilmiah, sebab penemuan ilmiah bersifat sementara dan terbatas, sedangkan Alquran bersifat abadi dan mutlak, atau
- Seseorang dapat menemukan berbagai kebenaran definitif dalam sains, dan hanya itu sajalah yang bisa dicari pembenarannya dalam Alquran.
Contoh dari sudut pandang pertama adalah artikel berjudul “Scientific I’jaz: Regulations and Limits” yang ditulis Fahd Al-Yahya (anggota terkemuka komisi internasional mukjizat ilmiah Alquran dan Sunnah). Dalam artikel tersebut, penulis memperingatkan orang-orang yang, misalnya, mencoba menemukan ayat-ayat seputar penaklukan ruang angkasa dalam Alquran, seraya menegaskan :
keraguan dan penolakan dari para ilmuwan-termasuk seorang ilmuwan Amerika-terhadap klaim NASA mengenai perjalanan pesawat berawak ke bulan sementara itu. kaum Muslim mengetahui bahwa bulan terbelah ketika masa hidup Nabi (hanya terjadi beberapa abad yang lalu), namun tidak ada teori ilmiah yang mampu membuktikan atau menjelaskannya. Karena itulah, klaim mengenai peristiwa tersebut masih selalu merujuk kepada kepercayaan ribuan tahun yang lalu [sic].
Sementara itu, sudut pandang kedua bisa diwakili oleh Abdellah Al-Mosleh (sekretaris jenderal komisi tersebut), yang dalam artikelnya “Regulations of Research in the Field of the Scientific Miraculousness of the Quran and the Sunnah“, mendaftar kriteria-kriteria berikut ini sebagai ukuran ‘validitas’ kesesuaian antara temuan ilmiah dengan ayat Alquran maupun hadis Nabi:
- Memastikan bahwa sebuah temuan ilmiah tertentu telah ditetapkan sebagai temuan yang ‘permanen dan bertahan lama’ oleh para ahli.
- Memastikan ketepatan makna teks-teks (Alquran atau Nabi) mengenai suatu fakta ilmiah tertentu tanpa istilah “kadaluarsa” dalam penafsiran teks sembari tetap menunjukkan bahwa pengetahuan tentang fakta tersebut mustahil telah ada ketika zaman Nabi.
- Menunjukkaan adanya bukti kesesuaian antara dua hal di atas yang harus didapatkan melalui langkah berikut:
- Membuktikan adanya fakta ilmiah dalam teks agama.
- Dalam hal Sunnah, membuktikan bahwa pernyataan Nabi itu sahih dan berasal dari ucapan Nabi sendiri.
- Membuktikan ‘validitas’ ilmiah sebuah fakta tertentu.
- Membuktikan bahwa pengetahuan tentang sebuah fakta muncul belakangan dan mustahil telah muncul selama masa pewahyuan.
- Membuktikan kesesuaian antara fakta ilmiah dan pernyataan agama.
Berbekal tinjauan mengenai sains, metode-metode, dan filsafatnya, serta Alquran dan prinsip-prinsip penafsirannya, kita tentu tidak sulit menyadari bahwa terpenuhinya semua ‘kriteria’ di atas merupakan hal mustahil. Contohnya sederhana saja. Apakah pendukung I’jaz menganggap gravitasi sebagai fakta alam yang sudah mapan dan teori Newton (hukum tarik-menarik antara massa) juga sebagai teori yang sudah mapan? Bukankah teori Einstein (relativitas umum) yang menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang dan menggantikan teori Newton yang juga dianggap sebagai teori yang mapan? Apakah teori Einsteinlah yang akan dipilih dalam hal ini? Pada titik apakah kita bisa menyatakan bahwa sebuah gagasan tertentu merupakan fakta atau teori yang sudah ‘mapan’?
Para pendukung teori ini -An-Najjar, At-Taftanazi, dan lain-lain- juga mengusulkan adanya pedoman dan kriteria validasi ‘penelitian’ jenis ini. Gagasan keduanya bisa dikatakan sangat mirip, karena itu saya lebih ingin membahas gagasan menarik lain yang disampaikan tokoh lain aliran I’jaz ini, yakni Abdulmajid Az-Zindani dengan kerangka teoretisnya yang terdiri dari dua metode berikut:
- Kebenaran kosmik sudah dinyatakan dalam Alquran namun tidak dipahami oleh umat Muslim, hingga kemudian ditemukan oleh sains. Kebenaran kosmik ini lalu menjadi akhir berbagai penafsiran ayat atau potongan ayat tertentu, kecuali jika ada pertentangan antara kesimpulan ilmiah dan makna yang jelas dalam sebuah ayat,
- Ilmuwan Muslim mengambil ‘petunjuk’ dari ayat-ayat Alquran dan melanjutkan penelitian ilmiah sampai dihasilkan penemuan baru yang menguatkan teks Alquran. Perhatikan bahwa Az-Zindani, dengan gaya khasnya sebagai seorang pemimpin konservatif, memberikan prioritas dan hak veto kepada Alquran atas berbagai penemuan dan kebenaran ilmiah.
Untuk memberikan paparan yang adil dan berimbang, saya akan mengatakan bahwa bahwa teori semacam itu -dengan berbagai metodologi dan klaimnya yang mengejutkan- tidak hanya eksklusif untuk Dunia Muslim. Para pengamat telah menunjukkan bahwa wacana defensif dan apologetik semacam ini juga telah muncul di kalangan kaum fundamentalis Kristen, kalangan kreasionis, dan beberapa fundamentalis Hindu.
Sebuah cahaya harapan bersinar dari Makkah pada Desember 2007. Dalam sebuah artikel yang sangat menarik terbitan jurnal Islamic Studies Universitas Umm Al-Qura (di Makkah), Saud bin Abdelaziz AI-‘Arifi memberikan kritik yang langka seputar teori I’jazdalam komunitas ilmiah agama. Pertama dan terutama, ia mengkritik metodologi teori ini serta menyebutkan segelintir contoh korpus I’jaz untuk menyoroti kesalahan faktual dan kegagalan mengikuti metodologi yang dipuja-puji oleh para pembelanya ini. Jika diringkas, gagasan-gagasan utama dalam artikel penting tersebut adalah sebagai berikut:
- Ada perbedaan mendasar dan besar antara pendekatan Alquran (yang menyatakan keberadaan Allah, kekuatan kreatif, dan keberlangsungan alam semesta) dan teori I’jaz (yang bertujuan membuktikan kebenaran Kitab Allah, yang setara dengan memperdebatkan kenabian Muḥammad).
- Ada suatu lompatan -kuantum konseptual yang besar antara menyajikan ‘argumen’ atau beberapa bukti (sugestif), seperti gaya Alquran, dan mencoba ‘membuktikan’ ke-berasal-an ilahi (alam semesta atau Kitab). Poin paling inti adalah bahwa pendukung I’jaz harus menantang siapa pun untuk menemukan ayat Alquran yang bertentangan dengan penemuan ilmiah atau pengetahuan yang sudah mapan;
- Banyak ‘penemuan ilmiah’ yang oleh para pendukung I’jaz diklaim juga terdapat dalam Alquran sebenarnya merupakan teori-teori yang sudah berkembang di kalangan fisikawan, filsuf, dan ahli ilmu alam kuno; yang terbaru adalah tingkat kedalaman dan ketepatan pengetahuan kita mengenai hal-hal tersebut.
Saya tidak sepakat dengan Al-‘Arifi hanya pada satu poin (penting): Ia percaya bahwa tidak ada ‘makna-makna ilmiah modern’ dalam semua ayat Alquran semata-mata karena Nabi dan para sahabat memiliki pemahaman penuh terhadap semua arti yang dikandung setiap ayat. Sebagaimana telah saya jelaskan, saya percaya bahwa Alquran memiliki beberapa tingkat pembacaan, sehingga ada banyak makna yang dapat ditemukan dalam ayat-ayatnya, bergantung pada pendidikan dan perkembangan zaman hidup seseorang. Seseorang bisa saja mampu membaca beberapa fakta ilmiah dalam sebuah ayat tanpa menggiring kepada klaim kemukjizatan (definitif). Begitu pula, meyakini bahwa membaca Alquran merupakan upaya yang terbuka atas semua kemungkinan, jauh lebih progresif dibandingkan klaim bahwa Nabi dan para sahabatnya mengerti semua makna ayat Alquran- dengan demikian, semua makna baru yang tidak diketahui oleh para Nabi dan sahabatnya tidak bisa diterima.
Terlepas dari itu semua, saya sangat kagum atas keberanian Al-‘Arifi, argumennya yang meyakinkan, dan usahanya yang kuat baik dalam melemahkan metodologi program I’jaz dengan berbagai kekurangan di dalamnya ataupun dalam mengkritik batas-batas tertentu ketika teori tersebut menjadi sejenis kebutuhan pokok kebudayaan Islam dewasa ini (penulis mengeluhkan popularitas dan dukungan finansial yang ‘terlampau’ besar untuk program tersebut, dan mengatakan bahwa mayoritas cendekiawan agama tidak menanggapi teori ini, tetapi hanya menahan diri dari berbagai kritik, karena takut dianggap menyerang ‘gagasan-gagasan yang telah kuat’).
METODOLOGI I’JAZ: DALAM PRAKTIK
Dalam bagian ini, saya akan mengupas bagaimana praktik I’jaz yang sebenarnya. Untuk itu, saya akan menggunakan contoh-contoh dari beberapa buku yang ditulis oleh para tokoh penting di bidang ini. Cacat-cacat metodologis yang dilakukan An-Najjar dan At-Taftanazi adalah sebagai berikut:
- Menegaskan bahwa sains merupakan sebuah ideologi, sehingga keduanya harus mengabaikan hasil apa pun -termasuk juga teori sains- yang tidak sesuai dengan pandangan ‘mereka’ mengenai alam dan kosmos. An-Najjar menulis:
Ada banyak teori tentang penciptaan yang telah melahirkan aliran-aliran ideologis yang berbeda: orang beriman, ateis, politeis, agnostik, rakyat yang bahagia, sengsara, dan stres, orang yang lurus atau menyimpang, dan lain-lain. Akan tetapi, seorang Muslim mendapat cahaya dari Tuhan yang ia peroleh melalui [pembacaan] ayat Alquran atau hadis Nabi. Cahaya tersebut akan membantunya memilih teori-teori yang membingungkan, kemudian mengunggulkan satu teori yang benar dan menjadikannya sebuah kebenaran yang mapan. Orang tersebut bisa melakukan hal yang demikian bukan karena sains yang menyatakan hal tersebut, melainkan karena isyarat yang ia peroleh dari teks-teks suci agamanya. Ia. berupaya membenarkan klaimnya dengan mengacu kepada kasus kosmologi modern sebagaimana berikut: “Dengan menyangkal teori penciptaan, para astronom modern menguatkan gagasan mengenai alam semesta terbuka (open universe) yang akan meluas kepada konsep kekekalan. Hanya saja, perkiraan mengenai massa yang hilang dalam perhitungan keseimbangan alam semesta justru membenarkan alam semesta tertutup (closed universe)”. Sayangnya, penulis tersebut melakukan kesalahan dalam paradigma kosmologis saat ini dan, tentu saja, juga melakukan kesalahan dengan mengklaim bahwa model-model dan hasil-hasil ilmiah merupakan produk ideologis.
- Mengklaim bahwa ketidakmampuan sains dalam memberi jawaban-jawaban definitif pada sebuah topik tertentu berarti mengakui bahwa fenomena dalam topik tersebut bersumber dari asal-usul ilahiah:
- “Sains-sains eksperimental menegaskan bahwa organisme hidup menyimpan sebuah rahasia sehingga alam semesta tampak sebagai sesuatu yang misterius bagi kita, karena kita mengetahui bagian-bagian sel dan materi penyusun tubuh manusia, tetapi sains toh tidak bisa membuat sebuah sel tunggal sekalipun.”
- “Pandangan sekilas terhadap berbagai sudut alam semesta ini, beserta segala hal dan makhluk di dalamnya, akan menegaskan kebutuhan adanya pengawasan dan pengamanan dari Sang Pencipta atas keberadaan alam semesta sepanjang waktu; karena alam semesta penuh dengan bahaya dan Bumi dikelilingi banyak ancaman dari segala sisi.”
- Mengatakan bahwa wilayah-wilayah tertentu dalam pengetahuan akan terus bersifat dugaan, tak peduli berapa banyak bukti material yang bisa dihasilkan: Tuhan dengan rahmat-Nya telah meninggalkan bukti konkret pada kita dalam bentuk catatan langit dan bebatuan bumi yang dapat membantu kita -dengan kemampuan kita yang terbatas- untuk mengetahui proses penciptaan. Model pemahaman semacam ini akan tetap bersifat teoretis dan dugaan, serta tidak pernah dapat mencapai status sebagai kebenaran, sebab kebenarankebenaran ilmiah harus muncul dari indera dan persepsi manusia [apa pun itu maknanya]. An-Najjar kemudian menggunakan pendekatan ini dan mengatakan bahwa alam semesta pastilah tertutup (atas dasar Alquran, Surah al-Anbiyā’/2I:104) tanpa mempedulikan hasil temuan penelitian kosmologis (yang sebenarnya).
- Memiliki kesalahpahaman yang sangat simplistis -jika bukan sangat serius-terhadap sains, khususnya fisika:
- Melambatnya percepatan alam semesta [yang merupakan kebalikan dari temuan sains mutakhir] menyiratkan bahwa gravitasi yang-pada suatu waktu hanya bisa diketahui Ailah -akan mampu mencegah perluasan alam semesta, menuntun ke arah penyusunan ulang semua materi dan energi dalam satu objek dengan kerapatan tinggi, yang akan meledak sebagaimana pada big-bang pertama, sehingga bumi dan langit yang baru akan muncul, sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Alquran, Surah Al-Anbiyā’/21: 104 dan Ibrahim/14: 48: (Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan semua manusia akan berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa dan Mahaperkasa.
- An-Najjar mencampuradukkan ‘materi gelap’ dengan ‘gas/asap primordial’. Tidak hanya itu, ia juga menganggap bahwa satelit Cosmic Background Explorer (COBE) -yang menghasilkan berbagai pengukuran akurat terhadap latar belakang radiasi gelombang mikro kosmik (sisa Big Bang) pada tahun 1990-an-telah mengamati ‘asap primordial’ tersebut.
- Meskipun ada daftar panjang referensi karya ilmiah yang dicantumkan di akhir buku An-Najjar, kita perlu mengetahui beberapa hal berikut: (1) hanya ada satu buku (dari sekitar 60 buku yang disebutkan) yang berusia kurang dari 10 tahun, yakni Powers of Ten, a flipbook; (2) karya-karya tersebut hampir tidak pernah benar-benar dikutip dan dirujuk oleh An-Najjar; (3) daftar referensi yang panjang tampaknya hanya bertujuan menghibur pembaca dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa koleksi besar dari referensi Barat telah digunakan (bahkan yang mutakhir) dalam buku tersebut.
- Sebagian besar karya An-Najjar (dan At-Taftanazi) memiliki strategi dan gaya penulisan berikut: memilih sebuah ‘ayat kosmik’ (pernyataan Alquran tentang berbagai fenomena alam), menyajikan belasan halaman berisi informasi ilmiah yang dapat ditemukan di ensiklopedia mana pun, barulah kemudian menyatakan bahwa benar-benar ada keajaiban (I’jaz) karena ayat tersebut telah meramalkan semua fakta ilmiah sebagaimana tampak dalam beberapa contoh berikut:
- Sungguh, Aku bersumpah demi bintang-bintang/planetplanetyang beredar dan terbenam (Alquran, Surah al-Kahfi/18: 15-16). Ayat-ayat tersebut dianggap merujuk kepada lubang hitam sehingga ia menyediakan 20 halaman teks plus 20 gambar berwarna sebelum berkesimpulan bahwa Alquran telah meramalkan eksistensi lubang hitam.
- Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang (Alquran, Surah al-An‘ām/6: 1). Ayat ini ditafsirkan dalam 13 halaman dari berbagai referensi klasik kemudian diikuti dengan 8 halaman berisi deskripsi rinci mengenai skenario Bang Big dengan berbagai tahapnya secara detail: usia quark dan gluon, usia nukleon dan antinucleon, usia nukleosintesis, usia ion, usia atom, usia bintang, dan usia galaksi. Penjelasan selanjutnya adalah deskripsi mengenai ‘kegelapan’: kegelapan primordial alam semesta; kegelapan kosmos baru-baru ini; kegelapan di kedalaman laut dan samudra, kegelapan di dalam rahim, dan kegelapan alam kubur. Benar-benar di luar jangkauan pikiran saya, bagaimana semua ini disimpulkan dari ayat yang disebutkan di atas.
- Dan matahari beredar di garis peredarannya/tempat beristirahat yang ditentukan untuknya. Masing-masing (Matahari dan Bulan) beredar dalam orbitnya (masing–masing) (Alquran, Surah Yā Sīn/36: 38 dan 40). Dalam pembahasan ayat-ayat ini, At-Taftanazi meluangkan 7 halaman untuk memuat informasi rinci mengenai matahari (massa, temperatur, komposisi, dan lain-lain) dan gerakannya (rotasi sekitar sumbu, revolusi di sekitar pusat Bima Sakti) kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ada kesesuaian ilmiah yang menakjubkan dengan ayat-ayat Alquran mengenai gerak sejati (bukan gerak semu) Matahari di ruang angkasa ataupun gerak revolusi orbital matahari di sekitar galaksi kita. Hal menakjubkan ini, tentang pergerakan matahari yang berbeda-beda, pastilah mengejutkan mereka yang mendalami sains/pengetahuan, dan pastilah akan menuntun para analis yang objektif untuk mengakui kemuliaan kitab suci ini.
- Dan telah Kami tetapkan manzilah-manzilah/tahapan-tahapan bagi bulan, sehingga (setelah sampai ke manzilah yang terakhir), ia kembali ke bentuk awal layaknya tandan yang tua (Alquran, Surah Yā Sīn/36: 39). Ayat ini, menurut At-Taftanazi, “jelas menyiratkan bahwa bulan berputar mengelilingi bumi yang mempakan fakta yang belum terungkap ketika Alquran diturunkan bahkan hingga berabad-abad setelahnya” (pernyataan ini dapat dengan mudah disalahkan dengan hanya dibandingkan sekilas dengan sejarah singkat astronomi).
- [Aku bersumpah] demi bulan ketika purnama, sesungguhnya kamu (bulan) melalui tingkat demi tingkat (Alquran, Surah Al-Insyiqāq/84: 18-19). Di sini, seperti yang mudah ditebak, perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan menuju bulan yang (diklaim) sebagai rumah.
Demikianlah yang terjadi dalam wacana I’jaz, ‘metodologi’ yang digunakan selalu persis sama. As-Syatibi -seorang teolog abad ke-14 dan ahli hukum yang telah disinggung sebelumnya- mengantisipasi berbagai penyalahgunaan semacam itu dan memberikan kritik berikut:
“Banyak orang melampaui batas dengan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak semestinya mengenai Alquran ketika mereka menghubungkan Alquran dengan semua jenis pengetahuan masa lalu dan masa kini, seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, dan logika. Sangat tidak dibenarkan menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak berasal dari Alquran sebagaimana juga mengabaikan sesuatu yang berasal dari Alquran”.
Seperti halnya Syatibi, ulama dan sejarahwan abad ke-13 dan ke-14, Al-Żahabi, juga mencela “inovasi-inovasi gila” seperti itu.
I’JAZ DALAM HADIS
Tidak terlalu mengejutkan jika baru-baru ini kita menjumpai sub-genre baru dalam literatur I’jaz yang menganggap hadis Nabi juga memiliki mukjizat ilmiah. Melawan sub-genre baru ini sebenarnya akan sia-sia meskipun ia memiliki cacat metodologis seperti yang disebutkan di atas -atau bahkan lebih buruk. Namun, saya merasa masih harus membuat para pembaca mengetahui dan menyadari sejauh mana kesalahan faktual dan metodologis -dalam karya-karya subgenre tersebut.
An-Najjar menerbitkan sebuah buku dua volume berjudul The Scientific I’jaz in the Prophetic Tradition (Sunna). Selama tahun pertama publikasinya (2004), dua volume tersebut masing-masing telah dicetak hingga tujuh dan lima edisi yang menandai betapa menakjubkannya popularitas buku-buku semacam itu di dunia Arab. Setelah memberi pengantar yang membenarkan perlunya ‘perlakuan-perlakuan ilmiah’ semacam itu, An-Najjar mengupas rata-rata 25 sampai 28 hadis. Ia menghabiskan sekitar 5 halaman untuk menyajikan berbagai versi yang berbeda dari sebuah hadis tertentu kemudian menghubungkannya dengan pengetahuan ilmiah yang diduga reIevan, lalu menyimpulkan bahwa hadis merupakan “pengetahuan manusia yang jauh ke depan, yang harus dipertimbangkan, selain mengimani kenabian Muḥammad .”
Sebelum menyajikan beberapa contoh khusus, saya akan menunjukkan masalah-masalah mendasar dalam metodologi subgenre tersebut: (1) meskipun dalam pengantar bukunya An-Najjar berusaha meyakinkan pembaca bahwa hadis yang dikutip adalah hadis yang sahih, asli secara historis dan tepat redaksinya, ia sebenarnya mengetahui bahwa dari waktu ke waktu, ada ribuan ‘hadis’ yang oleh para ulama Islam dianggap ‘dhaif’ atau ‘lemah’ serta sebagian besar hadis sahih yang memiliki banyak versi; (2) ia tidak pernah-bahkan tidak sekali pun-mencantumkan satu referensi atas klaim ilmiah besar yang ia kemukakan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari karyanya:
- ”Air sumur zam-zam (di Makkah) adalah obat untuk siapapun yang meminumnya”; An-Najjar mencantumkan daftar kandungan mineral zam-zam (yang sangat banyak), kemudian menyatakan bahwa air mineral tersebut baik untuk pengobatan berbagai macam penyakit (maag, gangguan pencernaan, masalah pembuluh darah, dan lain-lain). Tidak ada satu pun bukti atau referensi ilmiah yang ia berikan untuk mendukung pernyataannya tersebut.
- “Hari Pembalasan tidak akan datang sampai matahari terbit dari barat”; An-Najjar menjelaskan bahwa bumi telah lama dan masih melambat dalam rotasinya (pada porosnya), sehingga pada suatu hari, ia akan berhenti berputar dan mulai berputar ke arah sebaliknya! Namun, ia buru-buru menambahkan bahwa ini tidak berarti kita tahu perhitungan tanggal Hari Kiamat, karena hari tersebut akan terjadi “tanpa memandang hukum kosmik, perhitungan, atau melambatnya gerak bumi”! Banyak orang akan gagal memahami logika ini, dan hal ini setidak-tidaknya menunjukkan dua hal: (1) Profesor An-Najjar tidak mengerti tidal brakingyang menyebabkan sistem revolusi-rotasi terkunci (locking), bukan penghentian total; yang pasti, tidak ada pemutarbalikan arah rotasi; (2) dia tidak mau repot-repot melakukan penyelidikan ilmiah sistematis apa pun mengenai hal ini.
- “Bulan-bulan lunar (yang digunakan untuk peristiwa-peristiwa dalam Islam, seperti Ramaḍan) terdiri dari 29 atau 30 hari”. Berdasarkan hadis ini, penulis mengklaim bahwa Nabi tengah menyampaikan informasi yang hanya berlaku pada dua abad lalu (asumsi ini benar-benar salah dan sangat mudah dipatahkan oleh siapa pun yang memiliki pengetahuan astronomi dan sejarahnya). Ia juga mengemukakan bahwa pernyataan ini hanya mungkin dibuat ketika seseorang memahami perputaran bulan mengelilingi bumi dan perputaran bumi mengelilingi matahari; begitu juga rotasi bulan dan bumi pada sumbunya masing-masing-klaim yang secara keseluruhan salah. ”Allah menciptakan Adam dengan wujud yang sama, setinggi 60 hasta”. Di sini, si penulis mengatakan bahwa hadis tersebut adalah bukti lain kepalsuan teori Darwin selain adanya bukti fosil yang menunjukkan bahwa makhluk semakin mengecil seiring dengan berjalannya waktu.
MENUJU WACANA RASIONAL DAN KREDIBEL TENTANG ALQURAN DAN SAINS
Setelah mengupas semua pernyataan luar biasa dan metodologi-metodologi yang tidak konsisten di atas, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah: Mengapa teori I’jaz begitu popular? Menjawab pertanyaan ini secara meyakinkan bukanlah tugas yang mudah, sebab ia berkaitan dengan beberapa faktor sosiologis dan historis. Pertanyaan tersebut bahkan juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain semisal: Seperti apakah pemahaman umat Muslim saat ini terhadap sains? Seberapa tinggi level berpikir kritis dan analisis yang dimiliki oleh umat Muslim dewasa ini? Seberapa besar hasrat umat Mulism mengubah kekalahan di segala bidang menuju posisi yang terdepan dan unggul untuk meyakinkan diri sendiri bahwa agama dan peradabannya memang benar-benar unggul-dalam arti yang sebenarnya?
Tanpa memberi jawaban yang jelas atas pertanyaan kami tersebut, penulis kontemporer Mustafa Abu Sway melontarkan pernyataan menarik:
“Alih-alih mengejar sains dan mempertahankan statusnya yang tepat dalam perspektif Islam, tampaknya “tafsir ilmiah” (tafsīr ‘ilmī) memberi dampak yang menenangkan. Sementara di luar Dunia Muslim, siapa pun melakukan kerja sains, kita umat Muslim cukup menemukan kembali sains di dalam Alquran!”
Penulis Sudan, Bustami Mohamed Khir, menekankan adanya hubungan khusus dan sikap umat Muslim pada umumnya terkait dengan sains: “Pengalaman umat Muslim dengan sains berbeda dalam banyak hal [dengan Barat]. Daripada terus menolak sains modern, umat Muslim lebih baik berusaha menggunakan sains sebagai bukti baru untuk mendukung kebenaran Qurani.”
Sebagaimana telah saya tunjukkan, teori I’jaz Qurani berpijak pada prinsip-prinsip yang keliru, dan dua di antaranya yang harus diketahui adalah sebagai berikut:
- (hasil) penafsiran ayat-ayat Alquran bisa jadi tunggal dan pasti, sehingga sangat mungkin dibandingkan dengan hasil dan pernyataan ilmiah,
- sains bersifat sederhana dan jelas. Ia mengandung fakta-fakta definitif yang bisa dengan mudah dibedakan dari ‘teori-teori’.
Saya juga telah menegaskan bahwa teori ini merupakan produk dari rasa kebingungan yang awalnya muncul bertahap, tetapi saat ini sudah mengglobal. Yakni, kebingungan antara upaya yang sah untuk memadukan penafsiran teks dengan pengetahuan manusia yang baru ditemukan (tentu saja termasuk temuan dan wawasan ilmiah modern) dan prinsip bahwa hasil, hukum, dan penemuan ilmiah -mulai dari yang paling umum hingga paling khusus, bahkan misterius sekalipun- dapat ditemukan dalam Alquran dan bahkan dalam hadis jika dilakukan upaya pencarian ulang terhadap ayat-ayat tersebut dengan cara ‘ilmiah’. Teori I’jaz adalah bola salju yang dimulai dari bola kecil dan putih, tetapi 289 kemudian bergulung dan mengumpulkan kotoran (klaim yang sebenarnya menggelikan berdasarkan metodologi yang cacat). Teori tersebut juga bisa dianalogikan dengan segumpalan es kotor yang mudah meleleh di bawah cahaya -terang pengawasan metodis dan objektif.
Selain itu, saya juga menganggap pendekatan I’jaz berbahaya karena mengklaim bahwa seseorang dapat mengidentifikasi ‘fakta-fakta’ ilmiah dan membandingkannya dengan ‘pernyataan-pernyataan yang jelas dalam Alquran’ yang menunjukkan kesalahpahaman nyata terhadap sifat ilmu pengetahuan- Poincare mengatakan bahwa “sains bukanlah sekumpulan fakta seperti halnya sebuah rumah bukanlah sekadar sekumpulan batu bata”. Selain itu, teori tersebut juga mendistorsi pemikiran kaum muda Muslim dengan menunjukkan bahwa semua sifat sains dan pendekatannya harus diarahkan kepada Alquran.
Jika pada awalnya teori ini lahir dari sebuah gagasan menarik dan berharga (memanfaatkan sains untuk memahami Alquran dengan lebih baik), bisakah ia diselamatkan, dibersihkan, dan diarahkan -setidak-tidaknya untuk masyarakat umum-dengan cara merumuskan ulang teori tersebut agar bisa memunculkan pembacaan baru terhadap Alquran dalam konteks wacana hubungan antara Islam (teks-teks dasarnya dan warisan manusia yang dibangun berdasarkan teks-teks tersebut) dan sains? Saya rasa ini sangat mungkin, karena itulah di sini saya mencoba mengkritik sedikit demi sedikit pendekatan semacam itu.
Saya meyakini bahwa harus ada penggantian terhadap prinsip-prinsip keliru di atas dengan dua hal yang lebih tepat berikut ini:
- teks Alquran memungkinkan beberapa level pembacaan
- sains dan filosofinya harus dipahami sepenuhnya sebelum mengedepankan penafsiran teks agama yang mungkin memiliki relasi dengan sains.
Prinsip kedua sudah jelas: Seseorang harus mempelajari sains, khususnya metodologi dan filsafatnya dengan sangat baik dan tidak menggunakan sembarang pemahaman yang dangkal. Sementara itu, prinsip pertama jauh lebih penting bagi umat Muslim dalam pengembangan keagamaannya. Prinsip tersebut sangat mungkin menutupi berbagai kekurangan, mulai teori I’jaz hingga fundamentalisme (klaim monopoli kebenaran oleh beberapa pemimpin, ulama, atau aliran saja).
Prinsip pembacaan-bertingkat Alquran bukanlah isu yang baru, sebagaimana aspek-aspeknya yang telah kami singgung sebelumnya. Prinsip tersebut bisa jadi berakar pada zaman klasik Islam, khususnya Averroes dalam sebagian besar tesisnya, yang sering membahas kesepadanan antara filsafat dan agama, sehingga baginya, pembacaan Alquran dan penafsiran terhadap Hukum memungkinkan setidak-tidaknya dua tingkat pembacaan:
Pertama, pembacaan yang mendasar, umum, dan dapat diakses oleh sejumlah masyarakat; Kedua, pembacaan yang lebih mendalam, canggih, dan hanya bisa diakses oleh (kalangan) elite dan terpelajar.
Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana pendekatan ini digunakan untuk memahami Alquran dan sains, saya harus menjelaskan satu masalah terlebih dahulu: gagasan pembacaan bertingkat terhadap ayat-ayat Alquran mencakup -meski tidak terbatas pada- penafsiran metaforis yang harus digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Secara luas memang diakui bahwa beberapa pernyataan kitab suci tidak dapat diartikan sangat harfiah, semisal deskripsi antropomorfik mengenai Tuhan, meskipun beberapa penafsir konservatif menghindari pembahasan mengenai hal ini. Kita akan melihat dalam bab-bab selanjutnya bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena kosmik dan alam -termasuk penciptaan bumi, langit, kehidupan, dan manusia- juga akan membutuhkan penafsiran level tertentu.
Namun, gagasan mengenai pembacaan multi-level ini sebenarnya juga melampaui pendekatan metaforis. Hal ini terkait erat dengan prinsip lain tentang bagaimana Alquran menyikapi pelbagai jenis orang dengan kemampuan yang sangat bervariasi dalam memahami berbagai gagasan, utamanya gagasan mengenai kosmik dan aspek spiritual serta sosial. Karena itulah, bahasa Alquran harus mengakomodasi berbagai pikiran, kecerdasan, gaya belajar, dan zaman yang berbeda-beda tersebut. Karena alasan inilah, Alquran menggunakan berbagai frasa, pernyataan, dan cerita yang dapat dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Penafsiran yang beragam tersebut belum tentu semuanya ‘benar’, sebab tujuan penafsiran bukanlah untuk mencapai level akurat secara sempurna, melainkan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar.
Pertanyaan seputar kebenaran tafsir mempakan isu krusial sekaligus sensitif, sebab sebagian orang akan keberatan dengan implikasi implisit dari gagasan bahwa beberapa pernyataan Alquran barangkali tidak ‘benar-benar mutlak’. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa ‘kebenaran’ dan ‘akurasi’ hanya dapat dicapai dalam cara asimtotik. Hanya pencarian dan kemampuan untuk mencapai pemahamanlah yang memungkinkan kita mendekati kebenaran. Kita mungkin tidak pernah benar-benar mencapai kebenaran secara utuh, sehingga setiap kali menafsirkan sebuah ayat, kita mungkin hanya mencapai derajat keyakinan tertentu dari pemahaman yang ‘benar’ terhadap ayat tersebut. Yang terpenting adalah membaiknya pemahaman kita secara terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu dan usaha yang tak henti dilakukan.
Saya akan memberi beberapa contoh untuk menggambarkan gagasan ini. Alquran menyebutkan bahwa Nuh tinggal di tengah-tengah umatnya selama seribu tahun kurang lima puluh sebelum banjir datang (Alquran, Surah Al-‘Ankabūt/29: 14). Pada zaman dahulu, banyak orang beranggapan bahwa Nuh benar-benar tinggal di situ selama 950 tahun (arti harfiah), meskipun para mufasir klasik sering hanya menafsirkan bilangan tersebut dengan ‘waktu yang lama’ (Tafsīr Ibn Katsīr, misalnya). Namun, para cendekiawan belakangan (misalnya, Muḥammad Asad dengan tafsirnya) menunjukkan bahwa angka 950 juga disebutkan dalam Injil, dan Alquran menggunakan “unsur legenda yang berasal dari Alkitab tersebut” (menurut Asad) untuk menekankan (kepada Nabi Muḥammad dan kaum Muslim awal) bahwa durasi tinggalnya seorang utusan di tengah-tengah umatnya tidak pernah menjamin penerimaan umat terhadap ajaran utusan tersebut. Selain itu, harus diingat bahwa istilah ribuan bermakna ‘sangat lama atau panjang’ pada masa lalu.
Pertanyaan penting lain berkenaan dengan pembacaan metaforis/bertingkat terhadap ayat-ayat Alquran adalah perihal mukjizat. Seperti yang akan kita bahas pada tulisan selanjutnya, sejumlah besar mukjizat ‘fisik’ para nabi sebelumnya, misalnya Musa dan Isa, dewasa ini dapat dipahami secara lebih naturalistik. Misalnya saja, penyembuhan Isa terhadap orang buta dapat dihubungkan dengan efek plasebo (yang dipengaruhi pikiran), sedangkan terbelahnya Laut Merah oleh Musa dianggap sebagai kejadian meteorologis yang tiba-tiba. Sekarang, hal penting untuk dicatat di sini adalah bahwa pemahaman naturalistik yang demikian masih menyisakan ruang pemahaman yang terbuka, termasuk campur tangan ilahi yang menakjubkan. Dalam dua kasus tersebut, bisa saja muncul klaim bahwa efek plasebo (pikiran) dipicu oleh campur tangan ilahi pada tingkat kuantum, sedangkan kondisi meteorologis yang menyebabkan angin bertiup hingga air Laut Merah terpisah juga djsebabkan oleh intervensi ilahi pada tingkat mikroskopis yang kemudian menyebabkan butterfly effect/’efek kupu-kupu’ (sejenis chaos yang non-linear) dalam skala yang luas. Ada yang mungkin suka/yakin atau tidak suka/ meragukan penjelasan tersebut, tetapi saya pikir penjelasan yang demikian dapat menggambarkan pembacaan bertingkat terhadap ayat Alquran. Namun, ada juga beberapa mukjizat lain yang tidak dapat dipahami secara naturalistik, seperti transformasi ajaib tongkat menjadi ular yang mengharuskan seseorang menggunakan pembacaan level lain, yakni penafsiran metaforis. Untuk mendukung pendekatan ini, harus saya tambahkan bahwa dalam kisah Musa, Alquran terlebih dahulu menjelaskan bahwa ketika tongkat dan tali berubah menjadi ular, kejadian tersebut digambarkan dengan redaksi “tampak di mata Musa” (juga di mata orang lain), tetapi hal tersebut hanyalah tipuan pesulap, sehingga Tuhan menyuruh Musa melakukan tipu daya yang sama (bukan mukjizat apa pun) untuk mengalahkan para penyihir.
Pendekatan serupa dapat digunakan dalam membaca ayat-ayat Alquran yang tampak menyiratkan beberapa peristiwa ajaib dalam kehidupan Muḥammad, misalnya pernyataan bahwa selama perang Badar, seribu malaikat datang berturut-turut (Alquran, Surah al-Anfāl/8: 9) dikirim Tuhan untuk mendukung orang-orang beriman (yang kalah jumlah, dengan rasio 3:1). Inilah contoh lain dari aplikasi pembacaan multilevel: Para ahli tafsir klasik (misalnya Ibn Katsir ) sangat memperhitungkan cerita seorang sahabat yang mendatangi Nabi dan memberitahu bahwa beberapa orang kafir tampaknya meninggal karena pukulan aneh di kepala, kemudian Nabi mengatakan bahwa ‘itu adalah bala bantuan dari langit ketiga’. Sementara itu, para penafsir yang lebih modern (misalnya, Muḥammad Asad) menekankan aspek metafora terhadap penafsiran ayat tersebut dengan pernyataannya berikut ini: “Tentang janji bantuan ribuan malaikat, bantuan malaikat yang bersifat rohani tersebut jelas terungkap dalam kata-kata, ‘dan Tuhan telah menetapkan peristiwa ini sebagai sebuah kabar yang menyenangkan’.”
Contoh lain dalam pembahasan ini adalah kisah Isra’ Mi’raj Nabi, yakni perjalanan malam dari Makkah ke Yerussalem atau kenaikannya ke langit dan kembalinya (dalam satu malam) ke Makkah, sebab cerita ini tidak hanya sering dipahami secara harfiah, tetapi juga kadang-kadang digunakan untuk menghitung jarak bumi ke langit dan lain sebagainya. Mengenai peristiwa ini, penafsir klasik seperti Ibn Katsir menghubungkannya dengan belasan kisah, termasuk cerita Pendeta Yerussalem yang dipercaya menemukan bukti tentang “Nabi pernah melakukan shalat pada malam terakhir di biara kami” dan tentang “seekor binatang yang ditambatkan” di sudut tempat tersebut. Sementara itu, Asad melakukan pembacaan ‘mistis’ terhadap peristiwa tersebut dengan mengkhususkan seluruh bagian lampiran bukunya untuk menulis penafsirannya atas ayat Alquran seputar peristiwa ini.
Kemudian, bagaimana pendekatan hermeneutik multilevel ini diterapkan dalam wacana Alquran dan sains? Campanini memberi penjelasan berikut:
Kitab suci tidak mengandung pernyataan ilmiah maupun hukum alam secara eksplisit, sebab kebenaran-kebenaran yang diungkap Kitab suci disampaikan dalam bahasa yang sederhana, bisa dipahami masyarakat umum, dan juga terdiri dari kebenaran-kebenaran dasar yang dikemukakan sains dan filsafat dalam bahasa demonstratif yang tinggi dan indah. Karena itulah, menjadi hal yang absurd jika mencari pernyataan ilmiah tentang usia alam semesta dari Alquran, termasuk juga wacana apakah alam semesta diciptakan atau [kekal], terbatas atau tak terbatas.
Baiklah, mari kita gunakan pendekatan hermeneutik multilevel ini pada beberapa contoh yang paling sering dikutip dan menjadi favorit para penulis I’jaz. An-Najjar gemar mengutip ayat Dan Kami turunkan besi yang mengandung kekuatan hebat untuk berperang(Alquran, Surah aI-Hadīd/57: 25) dan mengklaim bahwa besi diciptakan di dalam bintang. Pernyataan ini benar adanya. Akan tetapi, penciptaan yang demikian juga terjadi pada hampir semua unsur alam semesta selain empat atau lima unsur dalam tabel periodik, dan-An-Najjar mengatakan -pada saat itulah besi tersebut ‘diturunkan’. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa informasi mengenai evolusi-bintang yang baru dikenal 50 tahun lalu jelas-jelas merupakan I’jaz. Namun, pada hakikatnya meteorit-meteorit pada zaman kuno telah sering ditemukan di gurun atau kadang-kadang terlihat jatuh dari langit dan diketahui mengandung banyak unsur besi (atau unsur logam lain), dan itulah bahan utama pembuat pedang. Karena itu, istilah besi ‘diturunkan’ dapat dengan mudah dipahami (seperti yang terjadi pada masa silam) sebagai unsur-unsur yang terkandung di dalam meteorit. Dewasa ini, beberapa orang mungkin lebih memilih penafsiran An-Najjar ini yang mungkin terlihat konservatif dalam pembacaan multilevel, tetapi bisa diamati bahwa besi merupakan bagian materi yang ada pada saat pembentukan tata surya, sehingga besi tidaklah ‘turun’ ke bumi (setelah pembentukannya). Itulah sebabnya, saya lebih memilih penafsiran besi sebagai meteor-yang menurut saya tidak ada unsur I’jaz sama sekali di dalamnya.
Ayat lain yang sering dikutip adalah langit yang berfungsi sebagai pelindung: Dan Kami telah menciptakan langit-langit sebagai atap yang terpelihara dengan baik (“saqfan mahfūżan”) (Alquran, Surah al-Anbiyā’/21: 32). Ayat ini biasanya dipahami secara berbeda dengan arti ayat-ayat Alquran, Surah Aj-Jinn/72: 8 dan as-Sāffāt/37: 7 yang bermakna perlindungan dari setan karena lebih diartikan perlindungan dalam arti ‘atmosfer, ozon, magnetosfer, dan lain-lain’. Dalam satu atau dua abad mendatang, siapa yang bisa menduga ayat tersebut akan ditafsirkan seperti apa. Yang jelas, jika dibaca dengan pikiran terbuka dan perspektif netral, sangat sulit melihat isi ilmiah di dalamnya.
Dengan menjadikan prinsip-prinsip dan aplikasi-aplikasi (atau contoh-contoh) ini sebagai dasar pembacaan terhadap Alquran dan sains, sangat jelas bahwa seseorang tidak bisa bersikeras pada satu penjelasan saja terhadap ayat-ayat tertentu, apalagi menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung kebenaran ilmiah. Namun, sebuah tafsir ilmiah Alquran bisa memungkinkan sebuah pembacaan tekstual berdasarkan informasi dan petunjuk dari pengetahuan penulisnya serta teori-teori sains yang ‘sesuai dengan pemahamannya’. Tafsir yang demikian adalah sebuah pembacaan di antara pembacaan-pembacaan yang lain, dan merupakan penafsiran yang setingkat lebih tinggi dibandingkan pengetahuan dan teori-teori sains. Tafsir yang seperti ini bukan lagi suatu I’jaz, melainkan -tidak kurang dan tidak lebih- merupakan kumpulan penafsiran-penafsiran pribadi yang beberapa di antaranya lebih meyakinkan (bagi sebagian orang) dibandingkan sebagian yang lain.
Sejumlah besar ayat Alquran -yang memuat ‘kiasan’ alam sebagaimana Alquran, Surah Āli ‘Imrān/3: 7 disebut sebagai ‘frase kunci dari semua frase kunci Alquran’ -‘menawarkan’ diri untuk (memperkuat) pendekatan ini. Di antara ayat-ayat tersebut, ada beberapa ayat yang begitu mengesankan para pendukung teori I’jaz, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan kosmos (Alquran, Surah Fuṣṣilāt/41: 11 dan lain-lain) atau perkembangan embrio manusia (Alquran, Surah Al-Mu’minūn/23: 13-14, az-Zumar/39: 6, dan lain-lain). Tujuh langit kemudian bisa dipahami sebagai orbit dari tujuh planet purba, atau beberapa galaksi yang saat ini kita kenaI sebagai kosmos -jika menggunakan teori multi-ayat- atau ‘dunia’ metafisik di balik alam semesta. Pembacaan-pembacan seperti ini akan menjadi urusan/opini pribadi yang bergantung pada pengetahuan dan wawasan masing-masing orang. Beberapa pembacaan akan tampak lebih ‘benar’ dibandingkan yang lain menurut kecanggihan pikiran tertentu, tetapi tidak ada dari pembacaan tersebut yang akan dianggap sebagai pernyataan ajaib karena mengandung pengetahuan ilmiah yang mendahului temuan manusia selama berabad-abad.
Singkatnya, saya ingin menekankan bahwa berdasarkan temuan kami, keseluruhan teori I’jaz mengandung cacat metodologis yang merupakan bagian dari teori itu sendiri, khususnya dalam praktik metode-metodenya serta dalam contoh-contoh yang telah saya kutip dari para penulis terkemuka di bidang kajian ini. Saya juga mencoba membuat perbedaan konstruktif antara tafsir ‘ilmi -yang berusaha menggunakan pengetahuan ilmiah untuk memunculkan penafsiran baru terhadap beberapa ayat yang menggambarkan alam semesta- dan I’jaz ‘ilmi yang mengklaim adanya fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan akhir-akhir ini dalam ayat-ayat tertentu. Gagasan ini saya gambarkan sebagai program utopis, baik dalam teori maupun praktiknya. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya mengusulkan sebuah paradigma baru yang secara potensial dapat memperbaiki semua kekurangan konseptual teori tersebut dengan menggunakan pendekatan baru dalam pembacaan Alquran yang saya sebut pembacaan multi-level. Asumsi sederhananya adalah bahwa makna yang dapat diungkap dari ayat-ayat tertentu bergantung pada tingkat pengetahuan/pendidikan dan perkembangan zaman hidup seseorang, sehingga mungkin saja ada seseorang yang masih membaca beberapa fakta alam semesta dalam suatu ayat tanpa mengklaim adanya mulgizat apa pun.
RINGKASAN DAN KESIMPULAN BAGIAN I
Dua gagasan besar yang saya tekankan dalam lima tulisan sebelumnya, terutama untuk pembaca Barat, adalah: (1) konsep Tuhan dalam Islam (dan bagaimana hubungannya dengan sains) dan (2) posisi dan pengaruh Alquran yang merasuk dalam kehidupan dan pikiran umat Muslim. Penekanan ini ditujukan untuk: (a) menjelaskan mengapa wacana sains dan agama (dan isu-isu sosial dan politik) di kalangan umat Muslim cenderung dipenuhi oleh berbagai referensi ayat Alquran; (b) menjelaskan bagaimana penekanan yang berlebihan terhadap ayat-ayat Alquran dapat menyebabkan distorsi berbahaya dan bergesernya wacana kepada persoalan ‘mukjizat ilmiah Alquran’; (c) menunjukkan bahwa agar wacana sains dan Islam yang rasional dan kredibel bisa diterima dengan baik oleh masyarakat umum maupun elite, maka perlu dipastikan adanya penerimaan terhadap Alquran (atau tiadanya penolakan) -jika bukan keselarasan penuh dengan ide-ide yang dibahas; dan (d) menekankan fakta bahwa Alquran dapat dibaca dan ditafsirkan secara rasional, setidak-tidaknya dengan satu di antara beberapa pendekatan yang bisa menyajikan sudut pandang yang juga rasional.
Memang diakui bahwa Kitab Suci berulang-ulang memancing perhatian pembacanya kepada ‘prediksi umum mengenai fenomena dunia fisik’, seperti dalam ayat: Matahari dan bulan beredar (secara tepat) menurut perhitungan, sedangkan bintangbintang maupun pepohonan juga tunduk kepada-Nya, dan Allah telah meninggikan langit dan menjadikannya seimbang (Alquran, Surah ar-Raḥmān/55: 5-7). Itulah alasan mengapa Alquran terus menerus mendorong manusia untuk mengamati, merenungkan, dan mencari.
Gagasan penting kedua yang muncul dari investigasi kami adalah bahwa meskipun Alquran memuat banyak perintah kepada manusia untuk mengamati dan merefleksikan fenomena alam dan hubungannya dengan Sang Pencipta, banyak orang masih kesulitan saat menghubungkan konsep sains (dalam pengertian modern) dengan wacana Qurani. Memang, konsep sains dalam pengertian modern tidak bisa ditemukan secara mudah di dalam Alquran atau bahkan di sebagian besar warisan klasik Muslim, sebab konsep pengetahuan sudah begitu berkembang. Perbedaan yang sebenarnya tampak subtil ini tidak menjadi bahan kajian bagi sejumlah besar pemikir dan pemerhati Muslim; bahkan kata ‘ilm saat ini sering digunakan untuk merujuk ‘sains’ meskipun cukup jelas bahwa kata tersebut pada awalnya lebih bermakna ‘pengetahuan’ dalam arti yang lebih luas. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan pendapat yang tajam antara kaum tradisionalis dan reformis mengenai kemungkinan (atau ketidakmungkinan) melihat kasus-kasus dalam Alquran dari kacamata sains dengan berbagai definisi sains yang ada, mulai dari ‘sains yang sakral’ (sacred science) hingga ‘sains Islami’ (Islamic science), dan bahkan ‘I’jaz ilmiah’ (scientific I’jaz).
Sikap pertama yang saya tunjukkan adalah penolakan terhadap semua perspektif yang ekstrem. Yang jelas, klaim seputar ‘pengetahuan ilmiah’ (mukjizat ilmiah) dalam Alquran itu harus ditolak karena berbagai alasan yang telah saya kemukakan sebelumnya. Sebaliknya, saya menekankan dan mempromosikan pembacaan berlapis (dengan nuansa dan petunjuk multilevel) terhadap sebagian besar-jika tidak semua-bagian Alquran. Pembacaan ini, bagi saya, dapat mencerahkan penafsiran seseorang terhadap ayat-ayat Alquran dengan menggunakan berbagai perangkat, termasuk pengetahuan ilmiah yang dimilikinya. Saya berpendapat bahwa pendekatan ini merupakan kombinasi yang tepat dari gagasan beberapa cendekiawan Muslim yang paling cerdas, mulai dari Ibn Rusyd (Averroes) hingga Muḥammad TaIbi.
Kami juga melihat bagaimana Muḥammad Syahrur melanggar aturan-aturan penafsiran tradisional bukan hanya dengan membangun sesuatu yang sangat orisinal dan pendekatan baru yang radikal terhadap Kitab Suci, melainkan juga dengan membuka gerbang penafsiran bagi siapa saja yang memiliki kapasitas intelektual untuk melakukannya, termasuk bagi non-Muslim dan para pengguna bahasa non-Arab. Lebih lanjut, ia juga memandang integrasi pengetahuan modern dalam proses pembacaan Alquran sebagai salah satu upaya memperluas potensi-potensi Alquran, membantu menyatukan masyarakat, dan mengharmonisasi pengetahuan masyarakat tersebut dengan kebenaran ilahiah.
Singkatnya, meskipun Alquran tidak dapat diubah menjadi sebuah ensiklopedi apa pun, termasuk ensiklopedi semua jenis sains, harus diingat bahwa jika Alquran dibaca dan dikaji dengan serius dan penuh hormat, maka resep hermeneutika dan prinsip Rusydian (Averroes) mengenai ketidakmungkinan pertentangan (antara firman Tuhan dan karya Tuhan) haruslah dijunjung tinggi. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat diubah menjadi pendekatan tanpa-keberatan atau tanpa-oposisi yang memungkinkan kita meyakinkan masyarakat Muslim mengenai gagasan tertentu (katakanlah misalnya, teori evolusi biologi) bukan dengan membuktikan bahwa teori tersebut dapat ditemukan dalam Alquran, melainkan dengan mengajak mereka melakukan pembacaan dan penafsiran yang cerdas terhadap beberapa bagian Alquran yang benar-benar konsisten dengan teori tersebut.
Sejalan dengan upaya mengembangkan pendekatan rasional terhadap Alquran (pendekatan yang begitu menghormati sains dan pengetahuan/penafsiran manusia), saya juga telah bekerja keras memberikan pemahaman yang jelas mengenai sains dan filosofinya. Dari pengalaman saya bergaul dengan para mahasiswa dan profesor di Arab atau Dunia Muslim, saya menyimpulkan adanya kebutuhan yang kuat untuk menekankan berbagai aspek kerja ilmiah, khususnya kriteria falsifiabilitas. Sains bukanlah sebuah proses mekanis, sebab ia dimulai dari prinsip-prinsip yang terkadang belum terbukti dan sering tidak bisa dibuktikan, bahkan cenderung bergantung pada insting pribadi, kecenderungan personal, konsensus bersama, dan mengikuti berbagai paradigma serta peristiwa-peristiwa ‘revolusi’ yang aktual. Saat ini, konsep dasar-dasar metafisik sains juga menjadi wacana umum. Dengan pemahaman yang demikian, menjadi semakin jelas bahwa sifat materialistik sains modern merupakan sebuah pilihan metafisik yang telah dibuat, tetapi bukan merupakan bagian dari proses ilmiah. Budaya-budaya masa lalu -tentu saja termasuk peradaban Islam pada masa ‘keemasan’ klasik-memang telah melakukan berbagai kegiatan ilmiah yang ketat dan sistematis, tetapi usaha-usaha tersebut masih bernuansa teistik dalam hal pandangan dan dasar-dasarnya. Mengembangkan sains dengan jubah teistik tidak selalu akan menghancurkan pilar, konstruksi, dan prestasi tinggi nan indah yang telah dicapai apabila seseorang melakukannya berdasarkan pemahaman penuh mengenai berbagai aspeknya, seperti membedakan aspek metafisik dari aspek metodologis. Itulah yang ingin saya coba tunjukkan dan kemukakan dalam tulisanselanjutnya.
Dalam tulisan selanjutnya, saya meneliti usaha-usaha yang pernah dilakukan para pemikir dalam membangun sebuah sains Islami, suatu kombinasi ganda (‘kuantum’) antara prinsip-prinsip Islam dan metode/hasil sains modern. Ada beberapa aliran pemikiran yang malang-melintang dalam wacana ini: mulai dari aliran yang sangat mistis (pendekatan sakral Nasr terhadap pengetahuan dan sains) hingga yang universalis dan konvensionalis (Abdus Salam) dan sekular (Hoodbhoy). Saya juga sempat mengulas singkat program Islamisasi pengetahuan/sains ala Al-Fāruqī dan Al-‘Alwānī dan menemukan kelemahan di dalamnya. Kemudian, saya membahas aliran Sardar (ijmali) mengenai sains Islami yang mengumbar janji-janji pada satu atau dua dekade lalu, tetapi belakangan kehilangan momentumnya -karena kelompok ini telah bubar. Meskipun menyatakan bahwa aliran ini paling dekat dengan posisi saya, saya menemukan banyak kritik terhadap gagasan Sardar, khususnya kecaman Sardar yang berlebihan terhadap sains modern, penekanannya yang berlebihan pada etika dan fungsi utilitarian sains, dan terutama gagasannya tentang ‘demokratisasi’ sains yang membolehkan setiap warga masyarakat berpartisipasi dalam proses ilmiah (misalnya, mengumpulkan data) dan perdebatan seputar wacana sains.
Pada akhirnya, posisi yang barangkali paling masuk akal dan moderat mengenai reposisi sains dan Islam adalah pandangan Golshani yang membela sains teistik, dengan kesadaran penuh akan (keberadaan) Tuhan, menjunjung tinggi tujuan-tujuan-Nya (sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Alquran dan lainnya), namun tetap bersikap seteliti mungkin. Gagasan Golshani ini, meskipun tidak begitu terperinci dan jelas langkah-Iangkahnya, cukup berjasa karena menyatukan upaya Muslim dengan para filsuf teistik dari budaya-budaya lain. Berbekal prinsip-prinsip ini dan pemahaman umum tentang Islam dan sains, saat ini kita telah siap membahas topik utama (kosmologi, desain, prinsip antropik, dan evolusi) secara panjang lebar dan topik-topik lain! (mukjizat dan tindakan ilahi) dalam bentuk semacam wacana pengantar.